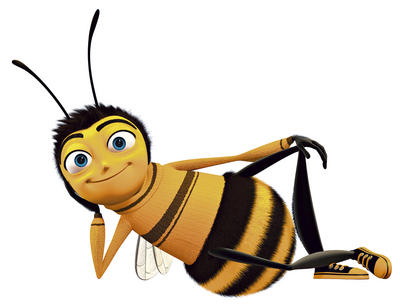Betapa banyak upaya yang dilakukan koloni-koloni bisnis dunia untuk ‘mengatur’ loyalitas konsumennya. Hingga di batas tertentu, kebutuhan akan berubah menjadi kesepakatan tanpa syarat antara modal dan konsumen. Bayangkan, banyak orang yang rela merogoh koceknya untuk membabat habis semua produk Harry Potter. Atau, berbangga ria dengan simbol-simbol besar seperti Coca Cola, Nike, Mc Donald, Walt Disney di seluruh aktivitas mereka tanpa dibayar sepeser pun. Ya, iklan gratisan. Dan asal tahu saja, semua itu dilakukan dengan ikhlas, tanpa tuntutan apa pun. Maka wajar kalau kemudian, di Wonogiri, banyak kita jumpai pribumi-pribumi millenium yang tiba-tiba sangat meminati pola-pola ‘bule kota’.
Dalam spektrum global, penetrasi modal dilakukan di seluruh ranah sosial, mulai dari kebutuhan pokok hingga ke isu pokok. Imperium global ini bahkan dilakukan berdarah-darah. Tilik saja kasus-kasus perebutan legitimasi seperti kasus Freeport, Exxon, atau Indosat. Atau hengkangnya raksasa elektronik Sony yang meninggalkan ribuan korban PHK dan bisnis-bisnis tersier yang berkaitan erat dengannya. Atau, banjirnya dana-dana sosial yang masuk ke kantong-kantong LSM. Belum lagi, bisnis senjata dan alat perang yang juga menggiurkan, transaksi minyak lepas pantai yang full kolusi, atau ... SBY yang memohon pada KADIN AS untuk investasi.
Sebenarnya, tak semua segampang di atas kertas. Realitas yang dibangun media tak selengkap dan tak sedetail di lapangan. Robert Heffner dalam Islam Pasar Keadilan terbitan LkiS Yogyakarta merunut publik Indonesia yang ternyata tak benar-benar memahami demokrasi atau globalisasi. Ia kaget kalau Samuel Huntington harus men-judge bahwa Islam dan Barat akan berseteru. Ya, Huntington terburu-buru untuk menyatakan bahwa sejarah akan segera berakhir dan demokrasi adalah pemenangnya. Karena, homogenisasi adalah kesalahan fatal dalam mentransformasikan mind share (ide-ide tentang penguasaan pasar) tertentu.
Tak jauh berbeda, bila tema yang dipersoalkan adalah liberalisasi baru modal dalam area global sekarang ini. Tentunya, tak semudah menyamakan persepsi tentang cara makan steak yang benar. Tentunya, tak semudah membuat tren tentang kerennya tank top hingga ke dusun-dusun terpencil di Gunung Kidul.
Pemilik modal berharap bahwa loyalitas adalah produk penting dalam menguasai pasar. Selain standar heart share (membuat konsumen merasa nyaman dengan kepedulian), mereka juga mendesain ideology share (membuat konsumen merasa loyal atas nama kebenaran). Namun, pola ini malahan membuat citra baru tentang homogenisasi pola yang membuahkan kebijakan memaksa, otoriter, dan menganggap komunitasnya sebagai yang terbaik.
Jihad dan Mc World karya Benjamin R. Barber terbitan Pustaka Promethea Surabaya menjelaskan banyak hal tentang fundamentalisme baru ini. Menurutnya, dunia telah dipenuhi dengan janji-janji idealitas yang berbuntut pada pemaksaan kehendak, bahkan mengeksekusi banyak kepentingan lokal untuk digulung bersama sentralisasi harga.
Jadi, niatan Barat dan AS untuk menjadi raksasa modal sebenarnya bukan perkara nilai (value) tentang keseimbangan dunia. Pemikiran dan terobosan ide yang didukung propaganda gila-gilaan hanya berefek pada segelintir komunitas di tanah air. Artinya, pada praktiknya, tak semuanya bisa diatur sentral. Dan ... yang pasti, mereka hanya bersemangat untuk mencari klaim pemikir (think tank); bukan benar-benar pemikir. Sebab, mereka, tidak lebih, hanya bisa berjualan tank top. Ya, think tank top. Sempurna, kan?
Sederhana saja, tentunya kita tak perlu berdebat tentang kemiskinan yang telah menggurita sebagai buah akumulasi modal atau berkuasanya konsumerisme. Adalah paradoks bila ribuan mall nangkring, sementara area kumuh tak pernah benar-benar digarap; kalau ternyata stok anak-anak putus sekolah yang mencapai jutaan. Nah!
Solo, 20 April 2006