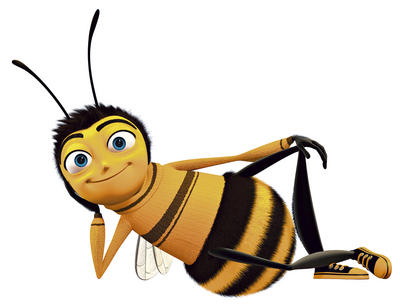Bila aku dan Hatta terhalang memimpin revolusi, saudara Tan Malaka melanjutkannya.
Soekarno, September 1945
Sebulan pasca Proklamasi....
Republik tengah sakit parah. Proklamasi yang telah dikumandangkan berbuah penolakan keras pihak penjajah Jepang. Ketika itu, hanya revolusilah yang bisa menyembuhkannya.
Adalah Tan Malaka, pria kelahiran 2 Juni 1897 di Sumatera Barat bernama lengkap Ibrahim Datuk Tan Malaka. Ia dianggap sebagai sosok yang sangat mengerti situasi, hingga Soekarno menempatkannya sebagai suksesor pengemban amanat revolusi. Dahulu, dia yang pertama kali mencetuskan kata ‘Republik Indonesia’ dan mengucapkan kata ‘Indonesia Merdeka 100%’ tanpa kompromi. Saat keadaan genting, terlontarlah kalimat di atas.
Lihatlah! Yang menarik tentu adalah ‘cara’ para pendiri republik ini bersama untuk menghalau penjajah. Soekarno sangat disegani karena ‘caranya’ berdiplomasi; penyambung lidah rakyat. Hatta sangat disungkani lantaran ‘caranya’ membela inlander yang tak tanggung-tanggung; Bapak Koperasi. Tindak-tanduk Tan Malaka bahkan sangat dikhawatirkan petinggi komunis dunia sejak Vladimir Lenin hingga Mao Tse Tung karena ‘caranya’ bergerak di komintern (komunisme internasional).
Ketiganya punya pendukung loyal. Ketiganya punya pemahaman dan kepandaian berbeda atas penderitaan rakyat. Perkara di akhir cerita, Soekarno berbeda dengan Hatta, atau Tan Malaka yang tak benar-benar diterima itu hal lain. Tapi mereka jelas punya ‘cara’ sama untuk menggelar revolusi kemerdekaan.
Gerakan Mahasiswa Pasca-1998
Lantas bagaimana dengan gerakan mahasiswa hari ini?
Pasca-1998, gerakan mahasiswa praktis mengalami penurunan tensi gerakan. Dari hari ke hari, kondisi ini semakin mengkhawatirkan saja. Sempat memanas pada gerakan penurunan Mega-Haz pada akhir 2002, gerakan mahasiswa kemudian kembali lesu setelah rakyat tak lagi tertarik isu penurunan presiden; seperti tahun 1998. Bila menjelang Pemilu 2009 mendatang, gerakan mahasiswa tetap belum mampu menjalankan fungsinya sebagai salah satu komunitas kritis pengawal perubahan republik ini, tentu ini tragedi besar.
Selain karena faktor internal gerakan, yakni masih belum mampunya berbagai elemen dalam memproduksi isu-isu populis seputar keberpihakan mahasiswa pada masyarakat secara luas, opini masyarakat tentang gerakan mahasiswa yang destruktif adalah fakta yang semakin menyudutkan keabsahan independensi mahasiswa di depan publik.
Karena masyarakat telah mulai tidak senang terhadap semua anarkisme dan euforia yang lahir dari interpretasi salah atas demokrasi, kecenderungan yang ada pun menunjuk pada stigmasi bahwa mahasiswa destruktif sangatlah tidak berguna. Sepertinya, kondisi objektif terang-terang tak lagi mendukung semua hal berbau mahasiswa. Tengok saja pemberitaan media massa yang lebih memilih ekspose tentang bakar ban atau kemacetan jalan akibat demonstrasi; bukannya isu yang mereka usung.
Minimnya aktivitas gerakan mahasiswa dalam melakukan kontrol terhadap semua kebijakan publik belakangan ini juga dilandasi oleh alasan yang sangat oportunistis. Mereka kesulitan menemukan format tegas gerakan lantaran beban status moral yang terus didengung-dengungkan oleh senior atau dosen sejarah mereka. Belum lagi isu kolosal tentang mahasiswa yang belum jelas masa depannya ketika lulus. Atau mahasiswa yang sering ditunggangi elite. Atau mahasiswa yang tugasnya hanya sekolah. Atau mahasiswa yang mending pacaran. Atau mahasiswa yang seharusnya riset saja tanpa kritisme terhadap sosial.
Fakta tentang konsentrasi agenda gerakan yang lebih didominasi oleh aktivitas personal bersifat individualistis menggejala kuat dengan mangkirnya berbagai aktivis mahasiswa dari agenda internal organisasi kemahasiswaan seperti perkaderan, advokasi, dan juga pemberdayaan publik. Ketika kritisisme dituntut untuk ada, kader-kader pilihan—bahkan terbaik—mereka lebih memilih untuk menjibakui kepentingan individu. Ada seloroh klasik, “Mikir diri sendiri aja belum bisa, kok berani-beraninya mikir bangsa. Presiden aja belum tentu bisa.”
Susah juga saat menyandang status mahasiswa tapi tak dapat mencetak sejarah besar. Namun ternyata tidak setiap zaman melahirkan kepemimpinan mahasiswa nyata, dalam arti perlawanan terhadap mainstream baik itu negara, modal, atau asing. Ada saat mahasiswa hanya di kampus, karena tak lagi direstui kondisi. Apalagi, kepala mahasiswa memang tak secepat kakinya. Praktis, semua hal tampak menjadi absurd dengan slogan-slogan membingungkan seperti agen perubahan, agen kontrol sosial, atau generasi penerus bangsa, dan seabrek identitas moral fantastis pemberian sejarah yang bisa jadi tidak lagi disandangnya.
Jadi, pasca gerakan reformasi 1998, ada beberapa hal yang bisa dicatat. Pertama, mahasiswa kesulitan mengawal enam visi reformasi. Pemerintahan Habibie, Gus Dur, dan Megawati memang disibukkan dengan gerakan mahasiswa yang menuntut penurunan presiden. Namun, setelah SBY-Kalla berkuasa, kritisme model ini tidak lagi menemui pasarnya. Publik tak lagi bersimpati dengan isu-isu serupa lantaran dikhawatirkan destruktif ketimbang menghasilkan solusi menjanjikan. Hasilnya, mahasiswa pun kesulitan menegakkan eksistensinya di mata publik.
Kedua, kampus-kampus excellent seperti UI, UGM, Unair, atau ITB didominasi oleh KAMMI, menggantikan HMI yang dulu dianggap beberapa kalangan sangat dekat dengan elite penguasa Orde Baru dan merestui kukuhnya kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun. Seperti diketahui, karena KAMMI adalah ormawa eksternal yang didesain untuk mengkover kaderisasi PKS di kampus, gerakan mereka lama-kelamaan mulai mengkristal mirip parpol. Padahal, umumnya, gerakan mahasiswa adalah gerakan ekstraparlemen yang tak akan mungkin bersekutu dengan parpol. Keberhasilan KAMMI mengubah konstelasi tentang mahasiswa yang bisa saja berparpol. Efeknya, bila mahasiswa tertarik berpartai, tentu nasib gerakan mahasiswa sebagai kelompok penekan akan menemui pola baru.
Ketiga, pasar bebas diberlakukan di Indonesia menggantikan kapitalisme negara Orde Baru. Kompetisi global akhirnya membaiat gaya-gaya neo-liberalisme seperti privatisasi, penghilangan batas-batas negara, dan berkuasanya informasi. SDM Indonesia, terutama mahasiswa, kesulitan beradaptasi dengan tren ini. Para mahasiswa pun tak lagi tertarik membicarakan gerakan mahasiswa, lantaran seperti tak berkaitan erat dengan masa depan mereka kelak. Rata-rata dari mereka berpikiran cepat lulus agar biaya pendidikan mereka tidak terus membengkak, sementara tak ada jaminan dari kampus tempat mereka belajar pada pekerjaan yang layak setelah lulus.
Gerakan Mahasiswa Menjelang Pemilu 2009
Beberapa hal dapat direkomendasikan untuk berhadapan dengan Pemilu 2009. Pertama, keinginan diri untuk tidak pernah berhenti belajar. Setiap kali realitas bergerak lebih cepat dari kemampuan analisis, harus pula segera diimbangi dengan proses cari tahu yang lebih gila-gilaan. Tanpa ini, adaptasi yang kurang akan melahirkan keinferioran peran yang justru kontraproduktif dan melahirkan fanatisme karena ketidakmampuan. Ilmu yang cukup akan melahirkan perhitungan langkah yang strategis hingga kemudian berani untuk berkompetisi. Sebab, lemahnya analisis akan semakin meminderkan gerakan, bahkan membangun fanatisme yang bisa jadi malahan destruktif.
Kedua, membangun kelompok-kelompok diskusi berikut silabus khusus pengembangan diri. Transformasi ideologis akan dapat dilangsungkan dan lahirlah komunitas kecil yang ideologis. Forum-forum kecil seperti ini dapat diarahkan pada pengembangan diri mahasiswa, baik intelektual maupun spiritual.
Ketiga, membuat akses strategis dengan melibatkan seluruh stakeholder gerakan seperti rakyat, kampus, pakar, tentara, polisi, politikus, kalau perlu negara asing. Seperti diketahui, fasilitas teknologi informasi dan komunikasi era ini sudah sangat memadai untuk membangun gerakan kultural, hingga politis. Koneksi ini tentu tidak untuk mengkhianati gerakan, tapi untuk menakar realitas kekinian yang tengah bergerak dan berujung pada perubahan sosial. Seringnya, membangun akses dianggap sebagai bersekutu atau keluar dari koridor moral gerakan.
Keempat, memiliki tren masyarakat informasi. Maksudnya, mahasiswa harus sadar pentingnya informasi, bagaimana mendapatkannya, bagaimana mengolahnya, dan bagaimana menggunakannya. Kemampuan berbahasa dan memahami teknologi tentu sangat dituntut untuk mencapai target ini. Sebab, gerakan yang tak up to date tidak akan direspons kondisi.
Kelima, memproduksi isu. Kemampuan mendesain isu dengan pembangunan opini dan pencitraan gerakan membutuhkan perencanaan dan kepekaan yang matang. Di sana harus ada kebutuhan rakyat, visi kebangsaan, dan cita-cita universal. Tanpa ini, isu yang diusung gerakan mahasiswa justru dianggap corong atau kepanjangan tangan pihak-pihak yang berkuasa.
Keenam, konsolidasi dan refleksi. Membangun kepercayaan terhadap kemunitas sangatlah penting. Untuk membangun tren yang begitu kompleks medannya, dibutuhkan dukungan berbagai pihak. Selain itu, evaluasi gerakan harus dilakukan untuk memonitor spirit dan perencanaan.
Ketujuh, komitmen dan konsisten pada semua yang telah diyakini dan direncanakan. Mulailah berusaha keras mematuhi hasil-hasil rapat kerja, tepat waktu dalam setiap event, bertanggung jawab pada semua hal. Bila persoalan pribadi seperti keseringan bangun siang, buang sampah sembarangan, malas bersih-bersih, atau sekadar malas tersenyum pada orang lain masih sangat merepotkan bagi aktor-aktor gerakan mahasiswa maka untuk mewujudkan civil society yang diridhai oleh Allah Swt. adalah pekerjaan yang sulit. Bangunan publik yang bermartabat harus diawali dengan integritas moral mahasiswa agar tak paradoks dan dapat bertahan lama.
Jangan Lupakan Ideologi
Kalau organisasi tak menghasilkan uang, mengapa harus ribut berpindah dari rapat ke rapat? Bila gerakan mahasiswa hanya menghabiskan waktu untuk berkumpul tanpa ada upaya membangun identitas diri, mengapa mesti nekat begadang hanya untuk lembur kepanitiaan? Andai kampus yang punya akses saja tak dapat menjamin masa depan, mengapa organisasi mahasiswa harus dibela mati-matian?
Sempurna. Sepertinya, gerakan mahasiswa layak dianggap bukan prioritas, lantaran tidak menghasilkan materi atau jaminan masa depan. Nah, dapatkah gerakan mahasiswa bertahan?
Lebih jauh, sebenarnya identitas diri jelas bukan perkara fisik. Meski ia akan memobilisasi fisik untuk beraktivitas, identitas lahir dari cara pandang tentang sesuatu. Cara pandang tersebut dapat disebut dengan nilai, ideologi, atau cita-cita keadilan dunia, dan setiap orang pasti memilikinya.
Mendudukkan nilai sebagai pilihan kedua setelah produk gerakan atau organisasi tentu adalah kesalahan. Sebab, bila hanya mempertaruhkan produk tanpa basis nilai yang cukup, ia tidak akan bertahan lama. FPI tak akan gagah berani membersihkan tempat-tempat maksiat bila tanpa pemahaman penting seputar nahi mungkar yang berbuah surga, sementara dalam satu waktu mereka harus berhadapan dengan kelompok yang mereka musuhi sekaligus polisi negara. Mahasiswa-mahasiswa kiri tak akan seberani itu menuntut nasionalisasi aset negara kalau tak ada doktrin tentang dominasi modal global yang semakin menyengsarakan rakyat. Perempuan-perempuan ber-fashion kosmopolit tak akan berpikir untuk berdandan sensual kalau tak meyakini bahwa seksi itu reputasi.
Artinya, tanpa ideologi atau basis nilai yang memadai, gerakan mahasiswa hanya akan menghabiskan waktu, melupakan masa depan, serta tak bergerak di wilayah strategis. Sedangkan untuk mencapai ideologisasi diperlukan proses transformasi yang kontinu dan berdasar pada kekuatan nilai yang komprehensif.
Epilog
Terkadang, mahasiswa dapat bersatu lantaran alasan moral yang sama, seperti perlawanan terhadap rezim represif, memerangi ketidakadilan, atau membela kaum tertindas. Terkadang, mahasiswa juga terkotak-kotak, tergantung perspektif kelembagaan mereka. Hal ini wajar mengingat kebijakan masing-masing organ yang memang independen. Artinya, meski berbeda, spirit kemahasiswaan mereka tetaplah terjaga sebagai bentuk perwakilan gerakan kaum muda yang tak menyetujui ketimpangan sistem sosial.
Saat Soeharto hendak digulingkan, semua elemen mahasiswa bernaung pada gerakan reformasi dengan isu yang sama. Ketika Soeharto dapat digulingkan, mahasiswa berbeda pendapat tentang Sidang Istimewa MPR untuk melanjutkan kepemimpinan negara. Pada waktu reformasi berhasil digulirkan, mahasiswa bahkan kembali pada perjuangan masing-masing atas kebijakan internal mereka; bukan lagi terorganisasi solid seperti sebelumnya.
Untuk itu, model gerakan mahasiswa memang harus berbasis pada independensi etis dan organisatoris. Maksudnya, ia bergumul atas karsa kebenaran universal (etis) dan bergerak pada wilayah oposisi (organisasi). Sementara itu, untuk bergerak, mereka mesti memosisikan organisasi pada ranahnya, yakni oposisi; bukan politik praktis mirip parpol; bukan advokasi murni mirip LSM; bukan orientasi bisnis mirip korporasi; bukan akademis murni mirip sekolahan. Semua wilayah itu dapat dirangkum dalam gerakan mahasiswa yang memosisikan mereka pada koridor belajar dan bergerak; bukan hanya bergerak atau belajar saja.
Gerakan mahasiswa juga harus plural dan inklusif. Ia akan dapat solid dan berkualitas bila menerima perbedaan dalam konteks saling mengisi, juga berpikiran terbuka sebagai bentuk kepercayaan sikap internal gerakan. Tanpa pluralitas dan inklusivitas, gerakan mahasiswa akan gampang dikibuli, ditunggangi, bahkan dikambing-hitamkan. Sebab, pada konstelasi perpolitikan, mahasiswa tetap sosok ranum yang selalu diperebutkan penguasa, stakeholders politik, tentara, bahkan CIA atau Mossad Israel.
Konsolidasi di tataran ormawa baik internal maupun eksternal kampus semestinya dijaga untuk membangun ritme gerakan yang bisa jadi tidak semulus di atas kertas. Kecurigaan pada organ-organ tertentu dapat dijembatani dengan membangun relasi positif; bukan malah saling merusak atau bersaing negatif. Sebab, komitmen gerakan mahasiswa tetaplah sama, yakni penjaga moralitas bangsa dan perwujudan masyarakat yang bermartabat.
Pemilu 2009 tinggal sebentar lagi. Kepemimpinan nasional akan sangat ditentukan oleh momentum ini. Bisa jadi, jual beli gerakan akan sangat dominan, tapi idealisme tentu tak akan lekang sampai kapan pun. Sebab, tak semua hal dapat dibeli.
Biarlah semua hal terjadi. Untuk kritis dan bergerak, bukan berarti mahasiswa tak dapat menikmati kesehariannya sebagai sosok manusiawi yang butuh dimengerti, anak rumahan yang berbakti, atau mungkin, musisi yang berbakat. Ya, menjadi gerakan ekstraparlemen altruis; pembela rakyat.