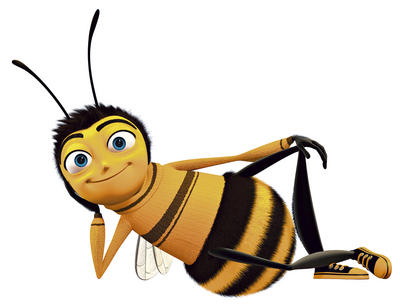Ideologi terasa usang setelah tesis Huntington seperti membelah kesumat kaum anti-Barat yang ‘seperti’ anti-kapitalisme. Sebab nyatanya, hari ini, kapitalisme justru berkolaborasi dengan globalisasi bertajuk kapitalisme global. Ia bahkan mirip senyawa yang terus beranak-pinak, dan membingungkan oposan-oposan sejatinya. Lihatlah, kapitalisme global ternyata menyimpan nafsu neoliberalisme yang sarat pragmatisme, individualisme, dan hedonisme. Isme ikutan yang kemudian turut nangkring dalam chart komunalisasi isme tak berujung itu melahirkan sekularisme, humanisme, dan pluralisme.
Lebih dalam, Thomas Kuhn memilih diksi ‘paradigma’ untuk menggantikan ideologi; genre baru adukan bermacam isme bernada ekletik yang membangun komposisi cita-cita ideal, dunia yang lebih baik. Publik yang semakin tak peduli pada isme, dan memilih sebentuk apa pun asal menyejahterakan, semakin membuat diskursus tentang ideologi menyusut drastis.
Meski beberapa negara masih yakin pada dua isme besar, kapitalisme dan sosialisme, tapi secara umum gejala menipis dan memudarnya ideologi semakin tampak pada realitas bernegara saat ini. Pada Musda HMI Jateng-DIY terakhir di Balai Kota Solo, Anas Urbaningrum mengutip pernyataan Menlu RRC ketika berkunjung ke Indonesia, “Menurut kami, ada kekuatan pasar yang bergerak dan sulit untuk kami lawan. (Ia sedang mendukung kapitalisme global. Padahal, Cina jelas-jelas komunis yang anti-kapitalisme) Kami tidak peduli apa nama sistem ekonomi kami… yang penting, rakyat kami bisa sejahtera.” Anas mengingatkan bahwa kapitalisme, sosialisme, atau apa pun namanya tidaklah terlalu penting. Dan hal yang paling penting adalah kemakmuran bangsa.
Ia juga mengatakan bahwa ada beberapa faktor kunci pembentuk kecenderungan dan kebijakan di negeri ini secara berurutan, yaitu ekonomi, kepemimpinan, budaya, birokrasi, dan agama. Betapa Anas memang khawatir terhadap nalar komunitas HMI yang terlalu haus kekuasaan. Sebab, baginya, ternyata, uanglah yang mendominasi negeri ini. Setelah itu, baru figur pemimpin, tatanan sosial, kemudian kekuasaan. Agama, secara nyata, hanya ditempatkan pada akhir analisis. Entah di posisi mana Anas menempatkan ideologi?
Pada 1999 silam, kepada kader-kader HMI Cabang Sukoharjo sewaktu berkunjung ke sekretariat pasca membuka Ospek UMS, ia berfatwa, “HMI tidak usah masuk ke dalam perdebatan soal gerakan kiri atau kanan. Yang penting dilakukan oleh HMI adalah mengembangkan kritisisme dan reproduksi intelektual.”
Lengkap sudah. Bahkan mungkin, bila ada diskusi tentang matinya ideologi sekalipun, tak akan banyak orang yang peduli.
Sebuah kalimat penting Cak Nur pun terngiang, “Kebenaran tidak akan bertentangan dengan sunatullah.” Artinya, bila ideologi bertentangan dengan sunatullah, ia akan hancur dengan sendirinya. Seperti diketahui, Cak Nur juga memberi tesis penting tentang Islam yang berbeda dengan islamisme. Ya, Islam tidak sama dengan ideologi Islam atau islamisme. Pada konteks ini, Islam akan menginspirasi lahirnya berlaksa-laksa ideologi, untuk kehidupan yang lebih baik. Artinya, ideologi hanya sejenis buah pikir, yang bisa saja terus diperbarui agar kontekstual. Ideologi tetap masih ada bila terus dikreasikan, dan… tak bertentangan dengan sunatullah.
Inisiasi
Beberapa waktu yang lalu, seorang kabid PTK/P Komisariat Umar bin Khathab (HMI Sukoharjo) berdiskusi banyak bersamaku. Ia hendak membangun cluster pertanian, dari pembenihan hingga market. Sederhana saja, ia bilang padaku, “Petani kita perlu eksis.” Yang menarik, dia bukan tipe based on state. Dia bukan tipe kader HMI yang tak bisa bergerak bila tanpa back-up sistem besar. Ia hadir tanpa peran negara, perusahaan, atau dana-dana sumbangan. Ia memutuskan untuk merangkul beberapa kawan, dan menyiapkannya, swadaya.
Ia bolak-balik Sleman, Solo, dan beberapa tempat di Jawa Timur untuk belajar dan menggelar simulasi pertanian, yang menurutnya menyenangkan. Ia tak hambar mimik saat membekap semua teorisasi tentang kemandirian, yang tak komplit, hanya karena sang teoretikus yang belum bergabung. Sebentuk kekurangcerdasan menyeimbangkan semuanya; keluarga, modal, menikah, dan mungkin... mengabdi.
Sejenak, aku mulai berkernyit pikir. Barangkali karena ia belum menikah, hingga ia tak sepusing kawan-kawan berstatus menikah. Ia juga baru hendak lulus, yang mungkin bisa dianggap belum berpengalaman. Atau yang paling nyinyir, banyak orang akan menilai, “Ia terlalu bersemangat.”
Apa pun, aku merasa perlu untuk memberitahukan pada khalayak tentang gejala baru yang barangkali bisa direspons positif. Untuk sebuah cita-cita tentang hari yang lebih baik. Aku tergiur bukan lantaran semangatnya, tapi karena sejak awal... ia berhasil mengetengahkan aktivitas pemadu kepentingan diri dan hajat hidup orang banyak.
Dulu, aku pernah bicara banyak pada salah seorang kawan tentang kemandirian rakyat. Sebuah diskursus rumit lantaran korporasi besar sering tak memberikan pilihan. Ada kesepakatan yang belum final tentang kemandirian dan pendidikan untuk masyarakat yang sedikit terumus, meski kemudian... hingga hari ini, semua masih saja di benak.
Aku pernah agak beralis tinggi sewaktu salah dua kawan menawarkan kewirausahaan. Bagiku, bila tanpa pemahaman keyakinan akan perlunya distribusi pendapatan, meski di beberapa hal ada tawaran pemberdayaan, ini akan menjadi akumulasi modal baru. Dan sejauh yang aku pikir, ini mengerikan.
Aku juga sempat bergerilia pilihan saat salah tiga kawan hendak menjadi pencari bakat bagi sekolah-sekolah asing di sekitaran Jakarta, yang menurutku, hanya melanggengkan dominasi modal dan korporasi besar.
Dialektika
Sebelum bicara lebih jauh, ada problem yang sering menjadi ikutan inisiasi. Aku menyebutnya, perilaku altruis yang jumawa. Altruis karena selalu berurusan dengan hajat hidup orang banyak. Menyelesaikan persoalan, salah satunya. Jumawa karena serasa sendiri hadir dalam semua aktivitas altruis itu.
Aku kutip sedikit tesis Madilog karya Tan Malaka bahwa masyarakatlah yang menentukan ide, bukan ide yang menentukan masyarakat. Problemnya bukan pada apakah ide atau aksi yang perlu didahulukan, karena keduanya diciptakan Allah Swt. berpasangan; tapi pada pemberian porsi lebih pada eksistensi manusia sebagai makhluk-Nya. Artinya, jelas bukan pada tempatnya bila ada yang merasa bahwa kedatangan seseorang untuk mengubah keadaan adalah lebih signifikan ketimbang kesadaran massa-nya. Simpulan ini juga mengantitesis pernyataan nihilis, “Semua pembahasan tentang perubahan datang terlambat.” Karena, perubahan terjadi karena banyak sebab, bukan hanya gagasan, inisiasi, atau ketokohan.
Aku setuju sebutan epistemic community, meski dulu slogan ini dipakai Rizal Mallarangeng untuk mengawal Neoliberalisme di awal 90an, yang jelas sangat tidak aku setujui. Aku memilih pola ini karena perlu menyatukan semua profesi untuk kepentingan yang lebih besar (semirip proletar).
Jangan pula lupa memosisikan ‘pemberdayaan’ yang kelak akan membuat semua ini terjadi begitu saja dan wajar. Pemberdayaan untuk komunitas, juga publik yang akan diberdayakan. Sekali lagi bukan lagi pada seberapa besar atau seberapa kuat sebuah komunitas mempengaruhi komunitas lain. Sebab, perubahan tidak terjadi oleh satu atau dua orang, juga bukan satu atau dua gagasan.
Kalau pakai paradigma pembelaan, barangkali aku lebih memilih untuk tengah berpikir membela komunitas dengan gagasan bersama, dan kemudian dapat memberikan pembelaan pada masyarakat lebih luas. Meski sekali lagi, aku tidak percaya perubahan terjadi karena ada ‘perasaan membela’ dari pelaku perubahan.
Itu dialektika.
Ideologi
Setahuku, ideologi ada dua jenis. Pertama, ideologi dalam pengertian praksis. Ideologi jenis ini komplit, dari episteme hingga praksis. Semisal, komunisme. Makanya ia mensyaratkan borjuasi proletariat pada fase revolusi pertama, untuk kemudian sampai pada sosialisme. Kedua, ideologi dalam pengertian world view. Ada derivasi kontekstual nilai yang pernah dirumuskan seseorang pada ranah tempat penafsir tinggal. Misal, ada demokrasi maka lahirlah Demokrasi Pancasila. Ada Islam maka ada NDP HMI. (dari LK II Kudus oleh anditoaja.wordpress.com)
Ketidakadilan selalu menjadi garapan setiap ideologi. Selain ada tujuan, ideologi juga memiliki metode gerakan dan aksi. Aku memilih untuk menjelaskan duduk perkara ini pada persoalan-persoalan di sekitar kita, yang sangat aku mengerti validitasnya, atau bukan dari data yang sayup-sayup. Semisal, setiap tahun akan lahir lulusan kampus, yang kemudian harus tercerai berai, bahkan mungkin bermusuhan, hanya karena tak ada orientasi gerakan pascalulus. Ada yang bilang, semua butuh aktualisasi. Aku setuju. Tapi alangkah lebih baik bila kemudian, kata kunci penting selanjutnya adalah sinergisitas. Sinergi ada setelah komitmen. Meski mungkin, suatu saat kita perlu kirim orang kita untuk mengabdi ke Mossad Israel, Wall Street AS, atau Berkeley, agar kita benar-benar tahu kekuatan dunia. Meski tentu banyak tak disukai.
Misal yang lain, berapa banyak kawan kita yang kemudian merasa tak cukup mampu mandiri, hanya karena ia tak bisa memecahkan persoalan hidupnya? Ada yang bilang, “Semua orang susah. Jadi jangan bermanja-manja. Itu harus dilalui.” Aku setuju. Tapi aku tak setuju bila ini lantas membelah semua komitmen kemanusiaan yang bahkan kita sepakati sebagai harus adil.
Itu yang paling dekat. Hingga suatu saat, kita akan bergerak untuk jutaan kaum miskin dan dominasi kapital dan state yang sangat sulit dienyahkan, hanya karena banyak orang yang merasa tak punya pilihan lain.
Revalague
Aku sempat berbahak sangka sewaktu memilih kata REVALAGUE atau Revolusi Ala Gue. Tapi bukan itu hal pentingnya. Aku setuju kata Tan Malaka tentang revolusi yang tak hanya diinisiasi satu-dua orang besar atau satu-dua gagasan besar. Eksistensi, individuasi, rausyan fikr, kader profetik, atau yang paling jauh khalifatul fil ardh berguna untuk mendukung terjadinya perubahan kolosal yang dimaksud. Jadi revolusi tidak akan terjadi bila para pelakunya sendiri tidak bisa menangkap eskalasi dialektika yang ada. Simpelnya, bila aku masih merasa bahwa Revalague itu final, berarti aku tak paham sunatullah. Bahwa analisis yang lahir untuk perbaikan kondisi adalah semata untuk ‘menebak’ jalur dialektika yang aku maksud, bukan pemaksaan kehendak, apalagi interogasi.
Pertanian, perempuan, anak-anak, atau apa pun bisa menjadi subjek diskursus, tapi tidak untuk dimenangkan salah satunya. Nah, epistemic community sebagai pola gerakan tidak hanya diposisikan sebagai pola ideologi (yang telah komplit bila bersanding dengan tujuan dan petunjuk aksi), akan tetapi juga sebagai pola runutan menuju bangunan ideologi yang saat ini belum jadi.
Lahirnya ideologi berkonsekuensi pada sebutan pembuatnya, yaitu ideolog. Padahal, marxisme baru ada setelah Marx dikubur. Kalo kata Daniel Dakhidae, penulis Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru, cendekiawan itu sebutan yang dilahirkan orang lain, bukan pendakuan. Walau nama ICMI mengantitesis ini. Pijakan tentang perlu lahirnya ideolog jelas bertentangan dengan dialektika. Jadi, aku tidak sedang menjadi ideolog, tapi aku masuk dalam epistemic community untuk menemukan pilihan juang, yang bisa saja dianggap ideologi.
Dari ketiga hal ini, ditambah ingin mencari format ‘adukan’, akan sulit mengatupkan semuanya pada sebutan yang hanya disebut ‘ideologi alternatif’. Lebih lanjut, nama tak perlu dikedepankan, hanya bila suatu saat, setelah sistem berpikirnya diketemukan, akan lebih baik bila disepakati saja. Jika agama punya surga, komunis punya sosialisme ilmiah, AS punya demokrasi dan welfare state, revalague tidak menyebut ini komitmen, atau supremasi (kaum strukturalis), atau kompensasi (pragmatis). Aku menyebutnya konsekuensi.
Sedikit pertanyaan yang bisa aku lontarkan. Akankah ada epistemic community untuk kemudian menggagas produk juang yang integral, lantas bermuara pada peran kemasyarakatan signifikan?
Pun saat ada yang bertanya, “Mas dan Mba, ada pekerjaan buat saya, ngga?” bukan berbalas, “Hidup itu ya harus berusaha. Jangan kebiasaan meminta-minta.”
Menurutku, itu berlebihan. Wallahu a’lam bi shawab.