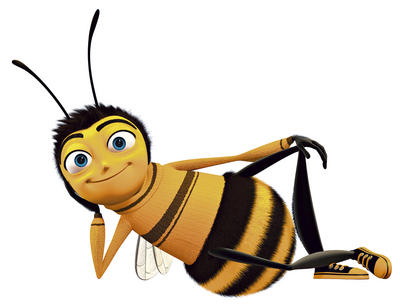Sabtu, 19 April 2008
Groovy
Kamis, 17 April 2008
Kesalehan Adalah…
Banyak orang berargumen wajar tentang pembelaannya terhadap kaum sengsara. Bagi mereka, tak apa seperti lilin yang harus membakar dirinya, asalkan dapat menerangi kegelapan di sekitarnya. Bagi mereka, pilihan untuk turun melakukan pembelaan adalah sebentuk tanggung jawab, bahkan beralasan moral penuh. Bagi mereka, waktu, pikiran, dan energi habis untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat kekurangan di sekitarnya.
Bagaimana kalau sekarang kita ganti perspektifnya? Dalam kasus Siti Nurbaya, menurut kamu, siapa yang salah? Ada yang bilang, Datuk Maringgih-lah penyebab semua kekacauan itu. Ada yang menyalahkan Syamsul Bahri yang tidak dapat berbuat apa-apa, untuk menyelamatkan Siti Nurbaya. Ada juga yang menganggap orang tua Siti Nurbaya terlalu tega pada anaknya, hingga harus menebus utang-utangnya dengan sang anak. Ada lagi yang menyalahkan Siti Nurbaya, karena ia hanya bisa pasrah.
Bagiku, siapa pun dapat salah dan dapat juga benar, tergantung alasan mengapa ia memilih pilihan itu. Datuk Maringgih tentu salah bila berusaha keras, bahkan dengan muslihat, untuk mendapatkan Siti Nurbaya. Tapi, Datuk akan tampak benar, bila ia dapat memberi solusi singkat, terhadap semua utang-utang ayah Siti Nurbaya, karena belum tentu sang ayah bisa membayarnya. Syamsul Bahri kelihatan salah bila hanya bisa ikut arus kondisi, tanpa ada tawaran solusi terhadap persoalan ini. Dan ia akan tampak benar, ketika ia sadar bahwa kekuatannya tak seberapa untuk menebus beratnya tanggungan utang itu. Ia tentu tak akan membawa lari Siti Nurbaya dan mengorbankan semuanya, hanya untuk cinta. Tentu saja, cinta tak akan bisa didapat dengan mengorbankan keluarga.
Ayah Siti Nurbaya bisa salah bila ia hanya mengambil jalan pintas, tanpa upaya keras mencari jalan keluar utang, bahkan mengorbankan anaknya. Namun, sang ayah akan dianggap benar, bila pada kenyataannya, semua utang tersebut memang diperuntukkan semua kebutuhan keluarganya. Sementara itu, Siti Nurbaya jelas salah bila ia bersikap tanpa alasan yang cukup sebagai bentuk identitas kebebasan memilihnya. Tapi, ia akan tampak bijaksana, bila semua itu dilakukan untuk pengabdian yang tak terkira pada keluarganya.
Nah, aku hanya ingin memberi poin penting tentang penentuan pilihan. Bila memang berbagi dan berjuang bersama orang-orang susah adalah pilihan, bukan lantas menempatkan kita sebagai sosok yang lebih bermoral atau setidaknya, menempatkan kita pada strata sosial baru, dengan reputasi sosial lebih. Biarlah itu Tuhan yang ambil peran. Biarlah publik yang menilai semuanya. Karena, yang penting, kita harus berbuat banyak. Begitu pun, kita tak akan pernah merasa bahwa semua ini penuh dengan hasrat menahan diri, mengorbankan banyak hal, atau terasa seperti pilihan yang berat. Itu tandanya, ada persoalan dedikasi yang bermasalah. Berarti, kita tak benar-benar ada dalam alasan pilihan yang tepat.
Bahwa akan ada jenuh, marah, lelah, atau berlusin kebuntuan serius adalah hal wajar. Namun, kebahagiaan yang tak terkira adalah ketika semua langkah diambil berdasarkan keyakinan yang sangat... dengan alasan yang mendalam.
Nah, berurusan dengan persoalan pelik seputar peluang kesejahteraan petani yang tipis, pengangguran, kesempatan kerja, akses modal, monopoli, hingga efek moneter yang berdampak krisis, jelas dibutuhkan dedikasi. Maksudnya, persembahan diri kepada Tuhan untuk berbuat yang terbaik; tak peduli apa yang akan terjadi. Karena, kebahagiaan tentu berasal dari dalam diri kita, bukan karena citraan orang tentang kita. Selebihnya, tak penting sebagai apa kita berbuat. Asalkan penuh dedikasi, itu sudah sangat membahagiakan diri.
Selisik Aurat
Aku suka Frida Lidwina dan Wanda Hamidah. Mereka smart, punya dedikasi, bervisi kebangsaan, dan istri yang baik. Penampilan mereka sejuk, meski tak berjilbab. Aku suka Jane Austen, penulis novel Pride &.Prejudice berkebangsaan Inggris. Ia mengabarkan pentingnya kebebasan memilih bagi perempuan, tapi ia sangat menghargai kesopanan dan menahan diri. Padahal, ia Protestan. Aku juga suka Zazkya Mecca. Ia berani berbeda dan buatku, itu perjuangan atas kebebasannya.
Berdandannya perempuan bagiku adalah identitas. Dan setiap orang tentu berhak mengabarkan identitasnya kepada publik. Perkara kemudian itu akan melahirkan stereotipe tentang sesuatu, seperti seronok, mesum, atau murahan, aku lebih tertarik untuk melihatnya lebih dekat (berpikir lebih dalam) persoalan ini, daripada memikirkan label-label sosial itu. Karena, identitas yang mereka bangun, jelas diperuntukkan pada eksistensi diri mereka sendiri, bukan untuk orang lain.
Perlunya dakwah tentang aurat akan sangat relevan bila kesepakatan tentang ini telah dicapai. Bukan berarti menganggap seruan tentang menutup aurat adalah salah. Sebab, berbicara adalah hak, asalkan tidak ada yang merasa dirugikan. Alasan moral agamanya, kita diwajibkan untuk saling mengingatkan, dengan dakwah salah satu variannya.
Nah, isu pornografi-pornoaksi boleh-boleh saja, dalam kerangka pembanding tren berbusana dan berbudaya; bukan komoditas politik-kekuasaan. Pelacur mana sih yang berani berdandan pas-pasan saat masuk gereja? Mereka pasti akan meninggalkan semua identitasnya itu di luar. Tapi, mengapa mereka tetap saja berperilaku sama setelah keluar gereja? Sekali lagi, semua itu untuk membangun identitas dirinya; bukan untuk orang lain, apalagi memanjakan orang-orang yang melihatnya.
Menurut Francis Fukuyama, kegagalan gerakan islamisme justru berbenturan pada kondisi islami yang telah lama ada di Eropa. Maksudnya, bagaimana mungkin Islam yang menjunjung tinggi kedisiplinan, kebersihan, dan kerapian bisa dianggap sebagai hal menarik baru, bila pada kenyataannya di Eropa keadaannya memang telah lama demikian.
Nah, yang lebih parah, gerakan anti pornografi-pornoaksi yang salah, bisa membagi orang-orang Muslim ke beberapa kategori. Ada Muslimah yang akhirnya merasa bahwa ia tidak benar-benar islami. Kalau dia lantas mencari tahu untuk belajar, itu lebih baik. Nah, semisal dia malahan merasa dieksekusi, bahkan dengan berondongan norma yang intens, barangkali ia bisa kehilangan kepercayaan diri, dan merasa tidak diberi kesempatan bertanya.
Mengamini Kecenderungan
“MAAF, HP saya sudah 4G (baca: four G), jadi ngga perlu pulsa kalau telepon,” tutur Onno W. Purbo, salah seorang pintar di negeri ini, dengan senyum renyah. Ketika itu, ia tengah diwawancarai sebuah TV swasta nasional, lantaran antena kaleng bikinannya bisa menjadi alternatif hotspot, untuk mengoperasikan internet di 22.000 sekolah terpencil. Terang saja audiens banyak yang melongo, berdecak kagum. Padahal, HP yang paling diminati di Indonesia saat itu baru berstandar 3G.
Onno jelas bukan satu-satunya orang penting dan sinting di negeri ini. Namun, ketekunannya yang luar biasa untuk menertawakan operator dan produsen HP, juga Google dan Microsoft tentu bukan hal sepele. Lihatlah, ia berhasil; dan citra republik supermiskin ini seperti tertunda sebentar karena kepintarannya. Onno hadir bersamaan dengan lusinan juara olimpiade dunia yang bahkan lahir di pelosok dusun Indonesia.
Di akhir acara ia berseloroh, “Untuk memajukan Indonesia, kita hanya butuh pemerataan teknologi informasi. Bila masyarakat telah benar-benar mendapatkan informasi memadai, AS atau Eropa bukanlah pesaing yang sulit.” Semoga ada tafsir baru tentang posisi kita yang lebih baik di kancah global.
Terbang jauh ke luar, Joseph E. Stiglitz, seorang peraih Nobel Ekonomi tahun 2001 untuk teori ekonomi dalam hubungannya dengan penyebaran informasi yang tidak sempurna (imperfect information), berpendirian bahwa tidak meratanya kepemilikan informasi menyebabkan kegagalan pasar sebagai institusi sosial. Akibatnya, jika keadaan ini terus berkembang, jurang antara si miskin dan si kaya akan semakin melebar.
Dalam bukunya, Making Globalization Work (2006), ia teguh berujar tentang dunia yang lebih baik, another world is possible. Ia tak seangkuh Francis Fukuyama yang gegap gempita mengampanyekan kemenangan kapitalisme dan demokrasi. Ia juga tak segalak Mazhab Frankfurt yang terus mempersoalkan keseimbangan pasar dan peran pemerintah.
Stiglitz memarahi Konsensus Washington yang percaya bahwa kebijakan ekonomi semestinya hanya berbicara tentang peningkatan efisiensi, dan there is no alternatives (TINA). Mereka percaya terhadap trickle down effect atau pemerataan pendapatan setelah tercipta konglomerasi, walaupun bukti-bukti empiris sedikit sekali mendukung premis tersebut. Mereka juga mengatakan, pemerataan ekonomi bukanlah urusan kebijakan ekonomi; itu adalah urusan politik. Dengan keyakinan yang salah kaprah tersebut, mereka mendorong globalisasi yang terbukti banyak memakan korban.
Belum genap semua itu, Muhammad Yunus hadir dengan Grameen Bank-nya dan menggusur semua ketidakoptimisan Nehru saat menggulirkan industrialisasi India serta meneguhkan tesis Gandhi tentang pemberdayaan kawasan pedesaan. Yunus seperti men-support tesis Talcott Parsons tentang fungsionalisme. Ya, semua orang punya fungsi masing-masing, siapa pun dia. Sama seperti Nurcholish Madjid yang mendudukkan universalisme pada kadar semua orang yang memiliki peluang sama atas anugerah Allah. Cak Nur lantas menggarisbawahi kualitas keimanan seseorang yang tidak melulu disimbolisasi oleh budaya—dan pada beberapa hal budaya itu bergeser menyamai fiqih.
Yang lebih penting, penjelas dari berderet fenomena menakjubkan itu adalah kesahihan Ar-Ra’du:11, Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah lho! So close no matter how far, kata Metallica. Setelah ‘berputar-putar’, ketemu kata ‘OK’ juga, kata T2—duo cewek keluaran idol TV show itu.
There is no ideology, anymore
Seorang kawan HMI Sukoharjo yang tertarik ingar-bingar teknologi informasi pernah berfatwa rigid, “Sorry, Bung. Hacker ngga punya ideologi.” Ia menjelaskan kompetisi dunia maya yang tidak lagi mengenal baik dan buruk. Tak ada lagi nasionalisme, kapitalisme, sosialisme, humanisme, atau isme-isme yang lain dalam belantara globalisasi informasi.
Deny, hacker imut dari Klaten yang mengacak-acak sekuritas KPU dalam Pemilu 1999 lantas dipercaya sebagai penjaga gawang keamanan data base KPU di Pemilu 2004. Sebelumnya, Deny dianggap penjahat karena merugikan negara, tapi setelah masa hukuman lewat, Deny tampak seperti orang baik yang tak tersentuh dengan memandegai data base KPU.
Katanya, situs porno hendak diblokir. Tapi bayangkan, miliaran situs porno yang telah ada itu akan terus bertambah setiap saat, bahkan pun bila harus ditutup per harinya. Roy Suryo, seseorang yang konon pakar telematika, bahkan berkata, “Hacker-hacker akan marah. Karena kebebasan berekspresi terhambat.” Entah apa maksud Roy. Yang jelas, perang hacker akan terjadi. Siapa melawan siapa itu tak penting. Pendukung siapa yang kemudian dianggap baik pun kemudian diserahkan kepada masing-masing kelompok. Relativisme!!
Agak meluaskan data, Tempo mencatat, nilai transaksi valas dunia mencapai 1.300.000.000.000 dolar AS per hari. Dari jumlah tersebut, hanya 2 sampai 3 persen dari nilai itu yang berkaitan dengan transaksi perdagangan dan investasi riil. Bayangkan, uang maya itu berputar dan bersaing bahkan bisa menghancurkan fondasi perekonomian sebuah negara atau institusi tertentu.
Kembali ke buku, Thomas Kuhn juga mulai meragukan peran ideologi dalam gerakan sosial. Ia memilih diksi ‘paradigma’ untuk memberi ruang bagi comotan berbagai ideologi ke dalam satu cara pandang (eklektik).
Anas Urbaningrum, sewaktu menjadi satu-satunya pembicara dalam forum pembuka Musda HMI Badko Jateng-DIY, di Balai Kota Solo Mei 2006 silam, mengutip pernyataan Menlu RRC ketika berkunjung ke Indonesia, “Menurut kami, ada kekuatan pasar yang bergerak dan sulit untuk kami lawan. (Sang Menteri tengah mendukung kapitalisme global. Padahal, Cina jelas-jelas komunis yang antikapitalisme) Kami tidak peduli apa nama sistem ekonomi kami… yang penting, rakyat kami bisa sejahtera.”
Anas mengingatkan bahwa kapitalisme, sosialisme, atau apa pun namanya tidaklah terlalu penting. Dan hal yang paling penting adalah kemakmuran bangsa. Modal berperan besar dalam menentukan kemakmuran suatu bangsa. Bagi Anas, ada beberapa faktor kunci pembentuk kecenderungan dan kebijakan di negeri ini, yaitu ekonomi, kepemimpinan, budaya, birokrasi, dan agama. Ternyata, uanglah yang mendominasi negeri ini. Setelah itu, baru figur pemimpin, tatanan sosial, kemudian kekuasaan. Agama, secara nyata, hanya ditempatkan pada akhir analisis. Padahal, HMI adalah pejuang syariat Islam—setidaknya menurut HMI keturunan Masyumi.
Menggunakan sudut pandang intelijen dan kontraintelijen, ideologi pun menjadi kabur. Bahwa Imam Samudera menghajar Paddys Sari Club dengan L300 penuh TNT adalah benar, tapi bahwa ternyata bom itu meledak berbarengan dengan bom lain yang memiliki daya ledak lebih besar itu pun banar. Hingga kini, publik tak tahu pasti, siapa yang meledakkan bom sebesar itu. Bahwa Iran anti-AS itu betul, tapi Pentagon juga main mata dengan beberapa stakeholders senjata juga tidaklah keliru. Bahwa isu pengadilan terhadap pelanggar HAM itu memang penting, tapi menetapkan kelompok-kelompok yang bernaung di bawah isu HAM sebagai kepanjangan tangan asing juga berlusin datanya. Siapa melawan siapa? Khalayak pun dibuat bingung.
Belum lagi di politik. Masyarakat tak lagi peduli partai apa atau siapa pun yang memimpin. Asal perut mereka terisi, siapa pun akan mereka dukung. PDIP yang katanya Sukarnois ternyata juga memprivatisasi aset nasional. Golkar yang katanya pro-pembangunan ternyata juga mendukung aliran investasi asing, bahkan dominan. PKS yang katanya partai Islam juga mendukung impor beras. Ideologi masih tampak sebagai polesan dan komoditas berpolitik.
Sunatullah dan Ikhtiar
“Kebenaran tak akan bertentangan dengan sunatullah,” begitu kata Nurcholish Madjid, seorang tawaduk tapi dianggap liberal oleh beberapa kalangan—termasuk kader HMI. Beliau pernah menyatakan pembubaran HMI. Tafsir bebasnya, andai tak dibubarkan pun, bila HMI mengingkari sunatullah, ia akan hancur dengan sendirinya. Misalnya, kemunafikan adalah biang kehancuran. Bila kader HMI tetap munafik, dengan menyatakan moral itu penting, tapi perilakunya justru amoral maka sederet kasus ‘biru’ dan ‘hitam’ pun mewarnai cerita-cerita dari komisariat ke komisariat, bahkan hingga PB.
Bambang Trims, Direktur MQS Publishing, salah satu mesin duit paling penting di Darut Tauhid-nya Aa’ Gym, bilang, kalau ia tak percaya tren (kecenderungan). Ia tahu, kalau di tiap masa selalu ada tren, tapi ia tak percaya kalau tren itu bisa direncanakan. Sunatullah kalau harus ada buku yang boom, dan ada yang tidak. Menurutnya, hal yang paling penting dalam bekerja adalah menjalankannya dengan hati. Keyakinan dalam melakukan sesuatu akan berefek pada kualitas buku, yang setidaknya bisa dipertanggungjawabkan ke publik dan Tuhan. Perkara akan menjadi tren atau tidak, itu urusan nomor dua.
Hernowo, tokoh sentral yang turut membesarkan Mizan, berkata bahwa idealisme harus diselaraskan dengan pasar. Pasalnya, daripada ide-ide besar itu ditolak mentah-mentah publik cuma lantaran tak bagus komunikasinya, mendingan agak memodifikasi komunikasi publik dengan standar yang tak terlalu elitis. Kepercayaan akan melahirkan simpati, baru kemudian penerimaan akan ide. Kalau sudah percaya, apa-apa pasti lebih gampang diterima. Beliau mengatakan, menulis itu bukan bakat yang telah ada (given). Aktivitas ini bisa dilatih dengan ketekunan. Boleh-boleh saja beranggapan kalau menulis memang given, tapi jangan pernah menghambat orang-orang yang punya pandangan kalau menulis itu skill; bisa dipelajari.
Rohman Saleh, Kabid PPA HMI Sukoharjo, mengajukan pernyataan, “Akhirat itu irrasional. Tapi, itu lantaran kita belum bisa merasionalisasinya, dan bukan tak mungkin, suatu saat akhirat akan menjadi rasional.” Maksudnya tentu pada upaya tafsir antara batas ikhtiar dan takdir, tapi alat analisis Derrida tentang Demarkasi Kebenaran tidak bisa Rohman tinggalkan. Di satu sisi, manusia butuh sandaran, sementara itu di sisi lain ketika sandaran itu bisa dirasionalisasi, keabsolutan itu akan pensiun. Dan persepsi yang menyamai Kebenaran tentu adalah kesyirikan.
Haruskah Kita Lelah Berdemokrasi?
Democracy grows into its being.
R.M. MacIver
Penulis buku The Web of Government
Letih rasanya mengungkap praktik demokrasi di negeri ini. Sebagai satu-satunya nilai dalam sistem pemerintahan yang hingga kini belum terbantahkan, demokrasi tampak untouchable, sakral, bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tak mungkin tergantikan, karena dinamika tafsirnya. Pada konteks ini, demokrasi selalu berada pada posisi yang selalu benar dan aksiomatis. Bila ada penyimpangan praktik demokrasi, sering kali dikembalikan pada proses telaahnya yang ‘mungkin’ belum sempurna; bukan pada penilikan ulang epistemologinya.
Begitulah. Di beberapa zaman, demokrasi bahkan menempatkan penguasa pada arogansi yang legitimate. Atas nama demokrasi terpimpin, Soekarno memantapkan posisinya sebagai presiden seumur hidup. Pada era Orde Baru, Soeharto bergerak selayak godfather di Istana Negara mengatasnamakan sakralitas Demokrasi Pancasila. Setelah era reformasi muncul, sebagian kalangan bahkan memaknakan demokrasi dengan kebebasan sikap yang berlebihan, dengan melupakan supremasi hukum yang ada.
Tampak jelas bahwa demokrasi selalu saja dapat berubah dari zaman ke zaman, sesuai tingkat interpretasi, juga kebebasan yang dimaksud. Tentu saja interpretasi dan kebebasan ala kekuasaan state. Sepertinya, tanpa halangan yang berarti, demokrasi bisa saja didesain sesuai keinginan penguasa. Betapa memang, untuk menyatakan diri sebagai ‘demokrat’ sejati ternyata tak harus berpijak pada tafsir tertentu. Asalkan tidak terlepas dari kaidah dasar demokrasi seperti keterwakilan kehendak umum atau ruang ekspresi publik, seseorang bisa saja menggunakan demokrasi sebagai alat kekuasaan.
Demokrasi Atas Nama Kekuasaan
Fakta tentang silang-sengkarut tafsir dan penerapan demokrasi yang selalu berubah akhirnya juga memaksa semua stakeholder bangsa untuk menyesuaikan diri. Tentu adalah hal sulit ketika harus menerima sejarah pembubaran Masyumi oleh Orde Lama lantaran dianggap sebagai kekuatan destruktif, perongrong stabilitas. Semua tahu, Masyumi adalah parpol Islam besar dengan seabrek potensi menjanjikan. Pada beberapa hal, parpol yang dimotori oleh Muhammad Natsir ini bahkan dianggap kampiun Islam Politik pasca Indonesia merdeka, bersanding dengan NU. Karena tafsir demokrasi Orde Lama yang tidak merestui langkah geraknya, Masyumi pun ‘dipaksa’ bubar.
Bukan perkara gampang pula bila kemudian banyak organisasi yang tidak berasas Pancasila tiba-tiba dibubarkan, karena dianggap ‘mengganggu’ negara. Ketika itu, Ormas dan parpol yang tidak berasas Pancasila dianggap sebagai kekuatan anti-Pancasila serta sah untuk dibubarkan. Berbondong-bondonglah semua organisasi di Indonesia untuk mengganti asasnya menjadi Pancasila. Sementara itu, beberapa kalangan yang tetap pada pendirian semula, lambat laun menuai kesurutan gerakannya.
Atau, tentang partai Islam masa kini, seperti PKS, PPP, atau PBB, yang tiba-tiba menerima demokrasi ‘islami’ ala mereka, dengan sedikit melupakan rigidnya perbedaan cara pandang kebangsaan dan agama sebagai ideologi negara. Seperti diketahui, isu tentang gesekan nasionalisme versus agama dalam konteks state telah bergulir sejak lama. Bila kemudian persoalan ini dapat dientaskan dengan mempraktikkan demokrasi yang menaungi semua asas, tampak bahwa tafsir demokrasi yang tepat benar-benar sangat strategis untuk mengakomodasi semua kelompok politik di republik ini.
Kalangan Islam Politik selalu beranggapan bahwa untuk memahami gerakan mereka, pandangan tentang pendikotomian Islam dan politik tidak akan berujung pada kesepemahaman bersama. Maksudnya, untuk membahas model gerakan yang mereka bangun, bahkan bersinergi, cara pandang dikotomis itu terlebih dahulu harus dihilangkan. Sampai kapan pun, keinginan untuk berjalan bersama tidak akan terwujud tanpa penghilangan dikotomi tersebut. Kalangan ini menyetujui keselarasan Islam dan demokrasi serta merestui berkecimpungnya partai politik berplatform Islam atau parpol berbasis ormas Islam untuk turut melebur dalam mekanisme demokrasi.
Praktis, dapat dirasakan bahwa sebenarnya ada indikasi kuat seputar interpretasi demokrasi yang disesuaikan dengan kepentingan kekuasaan, dan tentu saja untuk melegitimasi dan melindungi eksistensi politik kelompok tertentu. Artinya, sebagai mainstream, demokrasi terbukti berhasil mengondisikan semua wadah kepentingan politik untuk tetap meyakini kebenarannya. Sederhananya, bukan perkara penting untuk mengubah-ubah standar perpolitikan kapan pun dan dalam bentuk apa pun; asalkan masih mengatasnamakan demokrasi, sebuah negara akan ‘disepakati’ dunia sebagai penjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan anti penindasan mayoritas.
Demokrasi yang Terus Menjadi (Jadi)
Walaupun demokrasi masih dianggap sebagai nilai utama dalam kehidupan bernegara, ternyata tidak semua elemen masyarakat menganggap bahwa semua varian demokrasi wajib diikuti. Kasus-kasus seperti Golput pada Pemilu atau pendelegitimasian aparat negara semakin menampakjelaskan tentang lemahnya penerapan demokrasi, lantaran tidak lagi dianggap sebagai satu-satunya sistem negara. Secara de jure, bisa jadi banyak sekali ketentuan tentang penerapan demokrasi. Namun, secara de facto, tak banyak orang yang menyangkal bahwa semua ketentuan itu hanyalah syarat formal, tanpa makna.
Berbagai persoalan Pilkada langsung yang menuai kontroversi di sana-sini berbanding lurus dengan kebijakan politik ekonomi pemerintah untuk beras dan kedelai yang minim bargain. Munculnya banyak partai politik menjelang Pemilu 2009 seperti selaras dengan bingungnya rakyat pada upaya saling tuding elite politik tentang perjuangan yang sesungguhnya. Belum lagi semua dapat dikendalikan dengan prioritas yang terukur, krisis di Pakistan saat Benazir Bhutto terbunuh dan krisis Timor Leste saat terjadi upaya pembunuhan terhadap Ramos Horta semakin memafhumkan publik tentang kondisi demokrasi yang harus selalu beriring kekerasan.
Prasangka Ningrat Kaum Nano-Agraris
Kenyataan yang terbuat dari kontradiksi harus dibersamai senyuman, atau akan kita hitung sebagai kesalahan.
Jane Austen (1775-1817)
Penulis Novel Inggris, Pride & Prejudice
BETAPA sulitnya mengetengahkan ide teknologi pertanian ini. Simak saja, untuk menghasilkan produk pertanian yang berkualitas dibutuhkan teknologi yang memadai. Sementara itu, untuk mendapatkan teknologi yang memadai diperlukan biaya yang tidak sedikit dari keberhasilan pertanian yang berkualitas. Manakah yang lebih layak didahulukan? Vicious circle (lingkaran setan—red), akhirnya.
Tapi sudahlah. Itu epistemologi klise. Semacam membangun demarkasi kebenaran untuk mengaburkan pilihan. Lihat saja. Banyak hal di dunia ini yang sepertinya mutlak tak mungkin, tapi pada kenyataannya bisa dimungkinkan, meski dengan sangat perlahan dan saksama. Pada konteks teknologi pertanian, adalah pola pikir out of date bila kemudian semua itu dianggap tidak mungkin. Optimis dalam membangun konstruksi realitas baru tentu awal yang penting untuk membuat karisma pertanian negeri ini ke arah khittah-nya.
Semakin menurunnya harga, kualitas, akses pasar, dan preferensi konsumen produk-produk pertanian memang sebanding dengan rumitnya mengkomposisikan regulasi, pasar bebas, monopoli, juga transaksi valas. Semua itu berkelindan dengan tekstur moneter, fiskal, dan political will. Nah, seberapa pentingkah isu teknologi pertanian ini menyeruak ke tengah-tengah gegap gempitanya demokrasi, civil society, gerakan penghapusan utang, atau gila-gilaannya bisnis hiburan belakangan ini? Jawabannya mudah. Semakin banyak persoalan yang bisa diinventarisasi, tentu saja semakin menunjukkan kedewasaan bangsa ini di depan kenyataan. Sebab, langkah pertama menyelesaikan persoalan adalah dengan mengakuinya. Begitu tutur Liek Wilardjo, salah satu orang pintar di negeri ini.
Kaum Nano-Agraris
Belum lama ini, perkembangan teknologi mencapai maqam (tingkatan—red) baru. Di samping kesuksesan teknologi informasi yang bisa mengantarkan manusia ke dalam alam mikro dan makrokosmos sekaligus secara verbal, pesat juga dikembangkan teknologi hayati (biotechnology) dan teknologi nano. Menuju masa depan, ketiga jenis teknologi ini dapat disatukan dalam bingkai pengupayaan teknologi pertanian yang lebih mumpuni.
Teknologi hayati memberikan kontribusi penting pada budidaya varietas yang diharapkan bermuara pada lahirnya produk pertanian yang semakin unggul. Sementara itu, teknologi nano dapat diaplikasikan dalam bemacam desain mesin-mesin pertanian yang canggih. Seperti diketahui, teknologi nano adalah tahapan paling aktual dari rekayasa manusia atas susunan atom. Kata nano diserap dari istilah nanometer yang berarti sepermiliar meter (10 pangkat minus 9). Teknologi ini menumpukan perkembangannya pada produksi mesin-mesin canggih berdimensi sangat kecil. Ide nanometer berkembang dari ceramah Richard Feyman, peraih Nobel Fisika pada 1959. Menurutnya, materi dapat disusun atau diubah dengan memanipulasi atom-atom pembentuk materi.
Formulasi ini dapat dikawal rigid dengan reputasi oleh kaum Nano-Agraris. Maksudnya, kalangan yang permanen berurusan dengan pengembangan teknologi pertanian berbasis teknologi hayati dan teknologi nano, juga teknologi informasi. Kelompok tersebut membidani langsung peningkatan kualitas produk pertanian, serta distribusi dan pemasarannya.
Mereka tentu tak harus seberang gerakan Kiri Baru (new left), yang terlebih dahulu mempersoalkan dominasi pasar dan hegemoni negara atas praktik ekonomi yang ada. Tak perlu ada boikot, revolusi, nasionalisasi, atau mogok nasional. Kaum Nano-Agraris lebih diorientasikan pada penemuan daya saing yang tinggi melalui jaringan teknologi, hingga kemudian dapat bersaing dengan produk-produk pertanian asing, yang seringnya lebih didukung oleh regulasi ketat atau monopoli. Bukankah Eropa dan AS bisa sangat kaya, lantaran penciptaan ketergantungan yang sangat pada teknologi kreasi mereka? Jadi, bila kebutuhan akan teknologi itu dapat dipenuhi di sini, tentu bukan hal sulit bila harus menaklukkan pasar pertanian dunia.
Begitulah, mental unggul diperlukan untuk berkompetisi dengan dunia yang terkadang, tidak jujur dan penuh intoleransi. Hatta yang lebih memilih pulang daripada mengabdi pada Eropa di zamannya, dan berdampak pada kekurangkomplitan hidupnya, tidak lantas membuatnya memaksakan sepatu yang ia idam-idamkan. Ada upaya mendahulukan kepentingan yang lebih besar, tanpa melupakan keinginan pribadi untuk turut berbahagia. Sebab, bagaimana mungkin seseorang bisa memberikan yang terbaik bagi banyak orang, bila keadaan dirinya tidak sepantar dikategorikan sebagai sosok yang bahagia? Bahagia yang lahir atas dedikasi.
Atau kita sederhanakan saja bahwa bisa jadi, apple computers lahir karena ada keeratan filosofi antara pertanian dan teknologi. Itu sebabnya, lambang dan nama apel dipilih untuk memproduksi komputer. Nah! Wallahu a’lam.
Tunas Bangsa yang Dibajak
Paradise for me will be where there are neither paupers nor beggars, nor high, nor low, neither millionaire employers, nor half-starved employees, nor intoxicating drinks or drugs. Where there will be equal respect for all faith. (Mahatma Gandhi)
PROBLEM pendidikan signifikan hari ini adalah bagaimana menyelamatkan generasi penerus bangsa yang entah mengapa, lebih tertarik mengabdi kepada asing ketimbang leluhur dan tumpah darahnya. Sepertinya, telinga republik ini tak pernah kering disinggahi bermacam kisah tentang kesuksesan orang sebagai agen asing, dan tak lupa, menganggap diri mereka lebih tinggi dibanding kalangan sejawat yang mungkin, masih memilih untuk bertahan bersama setumpuk persoalan dalam negeri berikut gegap-gempitanya tuntutan diri seputar penyeimbangan idealisme dan kepentingan perut.
Sebagian dari mereka bahkan blak-blakan berkata bahwa
Padahal, pada beberapa hal, ketika benturan kepentingan terjadi, semisal citra
Meski harus diakui, ada sisi positif yang dapat diambil. Semisal, dapat disinyalir tegas bahwa sebenarnya, institusi pendidikan Indonesia memang layak diketengahkan di bursa aktualisasi dunia. Selepas bermacam kelemahan pendidikan yang hingga detik ini masih diperbincangkan, martabat bangsa mendadak tak pernah pudar lantaran prestasi anak-anak ibu pertiwi yang sering merajai pentas olimpiade fisika, kimia, matematika, bahkan sains dan teknologi. Beriring hinggapnya isu korupsi yang marak pada distribusi anggaran pendidikan, Indonesia juga memiliki banyak doktor, yang konon, banyak mengisi perguruan tinggi di negara serumpun, Malaysia.
Pun harus diakui jujur, bersama semua kelebihan itu, publik juga tak boleh menutup mata atas bermacam urusan pendidikan dalam negeri yang belum selesai, seperti peluang pendidikan bagi rakyat miskin yang semakin kecil lantaran biayanya yang terus melangit. Atau, banyaknya lulusan institusi pendidikan yang membludak, melebihi kesempatan kerja yang ada. Atau, anggaran pendidikan yang belum maksimal. Atau, tunjangan pendidik yang memprihatinkan.
Dilema Jaminan Kesejahteraan
Hal penting yang harus segera dipecahkan adalah tentang jaminan kesejahteraan yang terlalu minim di
Ironis tapi nyata. Membuat gelisah banyak pihak, tapi tak kunjung ada solusi. Ditambah lagi dengan kompetisi institusi pendidikan yang lebih mirip korporasi belakangan ini, peran kaum intelektual untuk berkonsentrasi pada aktualisasi diri semakin rumit. Setidaknya, mereka mungkin hanya akan melahirkan gerakan kecil, yang tentu akan lebih signifikan bila ditunjang dengan infrastruktur memadai.
Bagi para guru bangsa, tentu adalah hal naïf bila mereka harus banyak menuntut kesejahteraan dibandingkan pengabdian. Selain memang bukan itu tujuan mereka, ada idealisme suci yang terang-terang dapat membahagiakan mereka. Lihat saja, kisah tentang seorang guru di pelosok Nabire yang bahkan tidak mengenali Menteri Pendidikan di hadapannya. Ia hanya berpikir tentang sinerginya hutan dan sekolah. Itu saja. Atau, tentang sekolah Qaryah Thayyibah di Kalibening Tingkir Salatiga, yang sanggup memfasilitasi anak-anak miskin desa dengan internet.
Namun, dalam spektrum yang lebih luas, mengagendakan kesejahteraan mereka tentu merupakan bagian manajemen pendidikan untuk masa depan negeri ini. Sebab, telah nyata diketahui, bahwa lulusan-lulusan luar negeri, bahkan lulusan dalam negeri, justru merasa ngeri untuk mengabdikan diri di tanah air, lantaran jaminan kesejahteraan yang tidak memungkinkan bagi gagasan-gagasan besar mereka.
Bayangkan, bila kalangan yang mau mengabdi apa adanya bagi ibu pertiwi dapat dipertemukan dengan kaum ‘impor’ yang memiliki banyak penguasaan teknologi dan jaringan, tentu bangsa ini akan segera terlepas dari kerumitan persoalan besar. Artinya, mendudukkan perkara ini sebagai hal yang harus dipikirkan bersama tentu lebih bijak, ketimbang membeda-bedakan dua kelompok tersebut untuk dihadapkan. Betapa pada kenyataannya, dalam dan luar negeri memang perlu bersinergi, tentu dengan komitmen kuat untuk membangun negeri sendiri.
Apa Kabar Nasionalisme?
Sejauh ini, sudah selayaknya perlu dikemukakan kembali jati diri anak negeri sebagai bangsa. Artinya, seberapa pun dinamisnya realitas, setting goal tentang eksisnya bangsa tetap merupakan prioritas yang harus dikedepankan. Sebab, bagaimana mungkin bangsa ini bisa besar, bila tunas-tunasnya selalu dibajak kepentingan asing, hanya karena mungkin, akses dan komunikasi yang buntu? Bagaimana mungkin bangsa ini tidak didikte oleh bangsa lain bila generasi penerusnya masih gagu pada identitas kebangsaannya?
Logika sederhananya, kalau bukan anak bangsa yang memperjuangkan bangsanya, lantas siapa? Tentu saja bukan lantas bergerak pada penanaman identitas chauvinistis atau primordial. Sebab, cara pandang seperti ini juga bukan merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Harapan pastinya, semua kenyataan tentang rusaknya negeri adalah bagian tak terpisahkan dari perjalanan anak negeri. Jadi, secara pelan tapi pasti, sudah semestinya segera diselesaikan bersama-sama.
Beberapa kilasan sejarah dapat dikemukakan di sini. Barangkali, bila Hatta lebih menginginkan berkarir di Eropa, akan banyak tempat yang disediakan kaum borjuis di sana. Ketika itu, Hatta termasuk sosok yang diperhitungkan lantaran kebrilianannya. Namun, seperti yang diketahui bersama, Hatta akhirnya memilih untuk pulang ke Indonesia, dan bahkan, menyimpan hasratnya untuk memiliki sepatu yang ia idam-idamkan hingga kewafatannya.
Atau kisah seorang Sritua Arief, ekonom penganut neo-strukturalisme, yang gagasan-gagasannya sangat diterima di Malaysia, tapi lebih memilih untuk membesarkan beberapa mahasiswa di Solo dan Jogja, sebagai bentuk kefrustrasiannya pada utang luar negeri Indonesia yang terlalu besar dan rendahnya kredibilitas bangsa ini di depan kekuatan asing. Hingga maut menjemputnya, setelah diakrabi sakit stroke yang berkepanjangan, Sritua masih sempat berpesan, “Jangan pernah percaya dengan the borderless world.”
SEMUA ulasan ini tentu akan menjadi sangat sentimentil bila tidak segera disikapi lebih lanjut dengan tindakan nyata. Artinya, peran kalangan pendidikan bagi keberlangsungan bangsa ini di masa depan sangatlah ditunggu. Ketika banyak generasi cerdas ‘dibajak’ asing, sudah semestinya semua pihak merenung, berbicara, dan menuntaskannya, walau mungkin hasilnya nanti, tidak akan sesuai dengan yang diharapkan.
Komitmen keindonesiaan—salah satunya—masih ampuh untuk dijadikan pembenar bagi rukunnya jaringan pendidikan dalam dan luar negeri untuk berhadapan dengan gurita globalisasi yang semakin pintar memukul kalangan yang tidak siap berkompetisi. Biarlah sejarah republik ini terus mengalir dan bertemu dengan keberuntungannya. Bahwa memang, semua bangsa berhak untuk eksis di mata dunia. Bahwa memang,
Rabu, 16 April 2008
Merasa(kan) Miskin
Bandul waktu menunjuk bulan September 1965. Tampak seorang ibu berjalan menyusuri salah satu trotoar di Jakarta bersama anak laki-lakinya. Udara malam terasa sangat dingin menusuk tulang. Bangunan di kanan-kiri mereka tampak sepi. Mungkin sang penghuni telah berbaur dengan indahnya mimpi dan selusin harapan esok hari yang tak dapat ia gapai hari ini.
“Mak, ini Jakarta, ya?” tanya bocah laki-laki itu pada ibunya. Ia tampak terus melekatkan pandangannya ke langit kelam Jakarta yang dipenuhi suasana aneh, dan sepertinya belum pernah ia temui. Dengan mimik penuh apresiasi, perempuan berusia lebih dari setengah baya itu pun mengiyakan pertanyaan buah hatinya.
“Di sini banyak orang kaya ya, Mak?” tanya si anak untuk kedua kalinya. “Iya....” Kali ini, mereka berhenti di depan sebuah toko yang berareal teras cukup luas. Tentu saja toko itu telah tutup, lantaran hari sudah beranjak tengah malam. Setelah sedikit berbenah, dengan menggelar selembar kain untuk tidur, mereka pun berbaring di depan toko itu.
“Orang kaya pasti makannya enak-anak ya, Mak?” tanya sang anak sambil menatap ibunya. “Ya dong. Udah, cepat tidur! Jangan sampai kita bangun lebih siang dari pemilik toko. Biar kita tidak diusir lagi,” jelas sang ibu singkat. Mereka kemudian terlelap bersama balutan malam Jakarta yang belakangan dipenuhi resesi ekonomi dan sangat potensial melahirkan chaos.
***
Cuplikan kisah tersebut dapat dijumpai pada film klasik Indonesia garapan Arifin C. Noor tentang G 30 S/PKI. Di zaman Orde Baru, film kolosal ini menjadi tontonan wajib, setiap kali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Karena di zaman Orba stasiun TV swasta belum sebanyak sekarang maka praktis hampir semua mata di negeri ini pun melayangkan pandangannya pada scene-scene dramatis penculikan jenderal-jenderal TNI AD dan penumpasan G 30 S itu. Walau beberapa kalangan meragukan validitas film yang dikemas semi dokumenter tersebut, tetap saja tak mampu menghapus kenangan menyakitkan tragedi kemanusiaan seputar kudeta berdarah dan akhirnya konflik bersenjata antaranak bangsa tersebut. Sejarah kelam yang semoga tidak terulang kembali di masa datang.
Yang menarik, dengan bahasa yang sangat sederhana, Arifin seperti ingin menyampaikan pesan penting pada pemirsa tentang hubungan erat antara perasaan tertindas kaum papa dengan revolusi. Kesenjangan ekonomi pada waktu itu menjadi alasan kuat bertumbuhkembangnya ketidakpuasan, juga gejolak sosial. Jadi sebenarnya, bahkan tanpa doktrin marxis yang rigid pun, perseteruan antara si kaya dan si miskin tampak seperti keniscayaan bila kesenjangan itu dibangun atas ketidakadilan.
Arifin tentu saja melihat semua peristiwa mengerikan itu dari dekat. Ia dapat mendemonstrasikan semua ketakutan yang terjadi ketika itu dalam gambar, suara, dan skenario yang mengagumkan tentu karena ia sangat mengerti situasi yang berkembang, dan apa yang menyebabkannya. Ia mampu membingkai harapan banyak pihak tentang bangsa yang satu, tanpa ada lagi celah sikap—sedikit pun—untuk saling menyakiti, lantaran potongan-potongan kisah tentang kekejaman manusia yang haus kekuasaan itu benar-benar menghantuinya. Ia berpesan dalam gambar bahwa kalau tak hati-hati, korban akan berjatuhan seiring dengan kerakusan dan keserakahan anak bangsa yang satu atas anak bangsa yang lain.
Menyejarahkan Kemiskinan
Sepanjang waktu, mencatat kemiskinan memang pekerjaan sulit. Bagaimana tidak sulit? Siapa sih yang mau dianggap miskin? Siapa sih yang mau diperdebatkan penderitaan hidupnya lantaran kurang makan? Siapa sih yang bangga dengan predikat keluarga tidak mampu?
Deretan angka-angka pun berusaha menjelaskan kondisi riil yang ada seputar kemiskinan. Tapi, apa kata dunia? Banyak yang bilang, angka bisa saja dimanipulasi untuk mendongkrak popularitas. Ada yang yakin, kalau data-data kuantitatif itu hanya akal-akalan beberapa orang yang tidak menginginkan kemiskinan sebagai borok prestasinya. Bahkan ada yang ragu bahwa kemiskinan sering dijadikan komoditas untuk meraih simpati publik. Semacam pemahaman umum tentang ‘data yang diragukan’ bila telah berkutat di wilayah kemiskinan. Sekali lagi, ada tendensi prestisius seputar baik-buruk menyuguhkan kemiskinan di mata publik.
Tapi sudahlah. Bagaimana dengan kemiskinan yang memang benar-benar ada? Bagaimana dengan berita tentang korban frustrasi karena dibekap kemiskinan? Apalagi, bukan karena mereka yang tak bekerja keras. Apalagi, bukan karena mereka yang hanya bisa meminta-minta. Apalagi, bukan pula karena keserakahan mereka menjadi miskin. Apalagi, semua ini karena ketegaan sesama manusia yang memiliki perilaku takut miskin, berlebihan.
Lihatlah, dari tahun 1867 sampai 1878, Hindia telah menyumbang f187 juta bagi kas kerajaan Belanda. Sebuah angka fantastis bila dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat Hindia yang masih sangat rendah. Ketika itu, rakyat Hindia hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Hindia bahkan dapat menghidupi rakyat Belanda, walau mungkin, masyarakat negeri kincir angin itu tidak bekerja sama sekali.
Lihatlah, Orde Lama dianggap tak mampu menyejahterakan rakyat Indonesia dalam dua dekade setelah kemerdekaan. Orla dinilai sangat retoris, dan tak memedulikan penderitaan rakyat miskin. Inflasi yang mencapai lebih dari 600 persen di akhir pemerintahan Orla bahkan dapat dijadikan tumpuan untuk menganalisis keberhasilan orde ini mengurusi rakyat miskin.
Lihatlah, Orde Baru dianggap membangun infrastruktur ekonomi semu. Walau swasembada beras tercipta, harga-harga rendah, dan inflasi kecil, rakyat miskin tetap saja tak dapat dientaskan. Berpuluh tahun kaum miskin bahkan dianggap merepotkan pemerintahan kota besar. Gedung-gedung pencakar langit memenuhi sudut-sudut perkotaan, tapi nasib petani tidak jelas juntrungannya. Mereka bisa memproduksi beras dalam skala besar, tapi tak dapat memiliki komoditas lain, lantaran harga beras tidak sepadan dengan biaya sekolah, teknologi, transportasi, juga komunikasi.
Lihatlah, Orde Reformasi pun masih mandul membangun kerangka ekonomi yang stabil. Selain kedekatan mereka dengan modal asing, pembelaan mereka pada masyarakat miskin terjejali dengan dominasi agenda politik yang bertajuk demokratisasi tak terarah. Isu-isu tentang kemiskinan seperti hilang di tengah ingar-bingar manuver politik para pejabat dan wakil-wakil rakyat di parlemen.
Bila demikian halnya, Knut Hamsund, seorang novelis Norwegia awal abad ke-20, tiba-tiba menjadi sosok yang penting. Pada 1890, salah satu novelnya berjudul Sult (lapar), mampu membuat publik Norwegia terkesima. Novel ini bercerita tentang seorang penulis miskin yang sangat kesusahan makan. Setiap hari dia menggelandang di jalanan kota Christiania karena tak mampu membayar sewa kamar dan membeli makanan. Tapi, ia tetap menulis.
Kabarnya, Hamsund menulis novel ini dalam keadaan benar-benar lapar. Dan ia berhasil menceritakan kepapaannya itu dalam kadar optimistis yang sangat tentang hari yang lebih baik. Mentalitas tentang penyampaian isu kemiskinan kepada publik, tapi dengan keinginan kuat untuk berubah. Bukan malahan mengelak dari semua sejarah tentang kemiskinan.