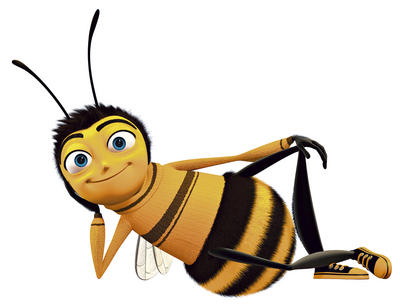Buta warna bukan penyakit. Banyak orang bilang, itu cacat. Bila penyakit bisa disembuhkan, cacat hanya bisa disiasati. Semacam upaya selektif untuk turut menikmati dunia, meski dengan fasilitas yang tak sempurna. Aku tak tahu persis, mulai kapan aku sadar bahwa aku… buta warna.
Semasa kelas 5 SD, aku pernah turut lomba murid teladan tingkat kabupaten. Aku senang bisa menceritakannya. Selain kemampuan akademis, para peserta lomba juga diwajibkan memiliki wawasan umum pilihan, kepekaan seni yang tak standar, dan kreativitas unik. Seingatku, meski tak menang di perlombaan itu, aku bisa mempersembahkan lampu flip-flop bikinanku sendiri.
Lampu flip-flop mirip lampu ‘awas hati-hati’ di jalan-jalan tertentu, dengan dua bulatan berwarna sama, tapi menyala bergantian. Ketika itu, aku merasa prakaryaku itu akan berhasil, meski dengan solder bekas dan timah yang diirit. Dengan bantuan seorang guru sabarku, ketika itu aku belajar memilih resistor dengan menghitung lingkar warna yang melilit tubuhnya. Untuk tujuan tertentu, kuantifikasi itu tak boleh meleset. Sebab, eksperimen pasti gagal. Pada skala besar, buatan pabrik memang lebih bagus kualitasnya. Tapi guruku ingin aku tahu betul, bagaimana pekerjaan itu dilakukan.
Nah, kalau aku bisa membedakan lingkar warna di tubuh resistor, berarti aku kan tidak buta warna? Aneh.
Sewaktu SMP, aku juga diapresiasi tinggi oleh guru elektroku. Pelajaran ini mensyaratkanku untuk tak salah memilih warna, selain hitungan berbau fisika. Kalau urusan PR, orang yang pertama kali beliau tanya pastilah aku. Bila aku tak ada masalah dengan PR yang ia berikan, berarti semua beres. Beliau tahu, seisi kelas biasa mencontek padaku.
Karena itulah aku memutuskan untuk masuk STM Otomotif. Selain bisa langsung berorientasi kerja, kabarnya sekolah itu tak banyak mengizinkan siswa-siswanya untuk hura-hura, tak seperti SMA kebanyakan. Faktanya, tes kesehatan memadamkanku. Mereka bilang, “Kamu buta warna separuh. Kalau diterusin, bisa-bisa kabel yang kamu sambung salah. Dan dhuar!!! Semua meledak,” jelas seorang guru pengetes dengan tertawa. Sebuah alasan yang masuk akal. Dengan sedih, aku pun bisa menerima kelemahanku itu.
Hikmahnya, aku kemudian banting stir ke SMA favorit di kota tempat aku tinggal. Tak seperti sekarang, dulu masa pendaftaran sekolah kejuruan seperti STM dan SMEA lebih dahulu daripada SMA. Jadi sangat memungkinkan bagiku untuk berpindah ke SMA saat tak diterima di STM. Toh, nilai kelulusan SMP-ku bisa memenuhi kualifikasi. Aku termasuk beruntung. Dari tempat tinggalku, hanya tiga orang siswa yang bersekolah di situ.
Pada satu kesempatan, guru biologiku memberi penjelasan sederhana, “Setiap manusia memiliki tiga tabung warna pokok di dalam matanya. Bila salah satunya rusak, bisa karena gen atau kecelakaan, maka ia tak bisa melihat warna dengan normal.” Belakangan aku juga pernah mendengar, kerbau dan buaya dikaruniai mata yang hanya bisa melihat dunia grayscale, hitam putih.
Setelah aku gagal tes masuk ujian perguruan tinggi negeri, sesuai arahan teman bapak, aku menuju Fakultas Geografi yang katanya terakreditasi A. Tapi, aku kembali gagal melewati tes kesehatan. Aku tetap saja buta warna separuh. Dokter ujinya bahkan kasihan melihatku kesulitan menjawab, warna apa yang tengah ia tunjuk.
Okelah. Barangkali Tuhan menciptakanku memang hanya untuk hitam dan putih, bukan banyak hal yang berwarna. Tuhan mengirimku agar aku berdiri tegak untuk hitam dan putih; baik dan buruk; benar dan salah.
Karena tak dapat menunjuk hijau dengan pasti, aku sangat kesulitan menerka kemakmuran ala bumi yang gemah ripah loh jinawi negeri ini. Aku hanya bisa membayangkannya dengan membangun konstruksi pikir tentang semua kebutuhan material yang selalu bisa didapat. Hijau buatku adalah saat semua kebutuhan sandang, pangan, papan, dan pendidikan terpenuhi.
Karena tak bisa mendeteksi coklat, aku kebingungan menengarai kenikmatan hidup. Meski aku doyan cokelat, tapi setelahnya aku bisa mual. Aku bisa terbirit bila ada durian atau sop kambing yang kata beberapa orang adalah masakan terenak di dunia. Aku berusaha mengimbanginya dengan menelaah musik. Meski bermacam aliran, musik tak memaksaku untuk tepat warna. Stevie Wonder bahkan jadi maestro meski ia tuna netra.
Karena tak bisa meyakini warna pink, aku tak seromantis orang-orang kebanyakan. Aku terbeliak nyalang bila melihat fokus dan keseriusan, tapi tak berkutik di depan puisi. Aku menjadi optimis dengan rasionalisasi pikir, tapi minder berat kalau harus menyapa manis, atau menemani orang agar tak bosan. Aku mendamba masa depan dunia yang lebih baik, tapi merasa asing pada keindahan yang dimaksudkan orang.
Tapi sudahlah. Bila memang demikian, aku akan tetap meneruskan hidupku. Karena jelas tak serumit bayanganku tentang penyandang cacat tubuh sejak lahir yang lebih menyedihkan, atau pengidap kanker darah dan AIDS yang hanya menghitung mundur hari. Toh, Tuhan akan menilai seseorang dari tingkat ketakwaannya, termasuk cara hamba-Nya bersyukur atas semua pemberian-Nya.
Aku hanya perlu meminta maaf pada orang-orang di sekitarku, juga yang sangat aku ingini, bahwa aku bukan sosok normal yang bisa menjelaskan indahnya laut, gunung, langit dengan deskripsi warna utuh. Aku hanya perlu meminta permakluman seumur hidup pada orang-orang di sekitarku bahwa aku sosok linier rasional, yang hanya bisa menerjemahkan sesuatu karena bisa melogikakannya.
Barangkali aku bisa berlatih, atau berbuat seperti yang orang lain perbuat. Terkadang aku ingin pandai melawak di depan orang yang aku kagumi sampai matanya mengecil dan tak sadar bahwa aku telah menghabiskan lima cangkir teh. Terkadang aku ingin dirasuki kemesraan yang sangat, bersama orang-orang yang berharap padaku untuk bisa berperilaku umum. Terkadang aku mengimpikan kekonyolan ekstra yang menggugah kesadaran agar setiap orang yang mengenalku tak pesimis hidup bersamaku. Terkadang aku ingin berbuat kecil tapi menyejukkan untuk orang-orang yang membutuhkan kehadiranku.
Namun, berlatih yang aku maksud tak bisa menyembunyikan kecacatanku. Aku bisa saja mereka-reka keindahan yang diingini orang dengan imajinasi yang aku bangun atas keterangan orang atau buku yang pernah aku baca. Tapi aku tak akan sesempurna mereka yang benar-benar dikaruniai dengan… memahami warna penuh seluruh.
Mungkin saja, aku hanya butuh kepercayaan bahwa aku yang tak bisa mendeteksi dunia berwarna ini sebenarnya sangat ingin membahagiakan orang lain, meski tak akan benar-benar nyata seperti umumnya.
Setidaknya, aku akan selalu bisa memaklumi semua hal tak indah yang mampir di kehidupanku. Sebab, aku sadar, sebenarnya aku tak pernah benar-benar bisa menangkap keindahan yang dimaksud orang lain. Aku tahu dunia itu berwarna, tapi aku tak sanggup menunjuknya.