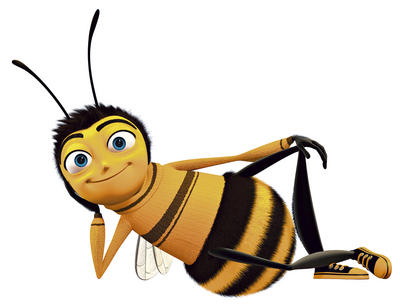Andrea Hirata, penulis Laskar Pelangi—penisbah fungsi pelangi yang tak selalu melangit tapi juga sangat bermakna bagi perjuangan kaum kurang—pernah berujar, “Pagi itu hujan turun deras. Saat datang ke sekolah, saya lihat Bu Mus datang dengan berpayung daun pisang. Saya kemudian berjanji dalam hati bahwa suatu saat, akan saya tulis buku tentang ibu guruku ini.”
Sederhana tapi menyentuh dasar keterenyuhan insan akan peliknya kekurangan. Tak muluk-muluk tapi melampaui cita-cita ideal tentang hidup yang harus selalu lebih baik. Umum tapi mengingatkan kadar religisiutas yang semakin tipis dalam benak masyarakat gila materi seperti sekarang. Jauh dari ekspresi meledak-ledak tapi menggerus keinferioran mentalitas kalangan yang sepertinya tak pernah berpeluang.
Dan setelah semua semakin baik, dengan sekuat hati Hirata pun menuliskan berjejal kenangan mengagumkan tentang arti pengabdian itu pada enam minggunya yang berkesan. Lahirlah novel yang menginspirasi banyak punggawa kemanusiaan itu dengan selusin kesederhanaan menjanjikan seputar reputasi hidup, yang bersudut pandang berbeda.
Sebenarnya, Hirata tak pernah berkeinginan menawarkan bukunya itu ke penerbit komersil, apalagi hingga difilmkan. Ia hanya berkeinginan untuk mengikat sejarah masa kecilnya itu dengan tulisan, untuk kemudian difotokopi dan dipersembahkan kepada Bu Mus, sosok yang sangat menggugah makna kesungguhan dirinya untuk terus berbuat baik dalam kondisi sesulit apa pun. Ini dari hati ke hati. Ini tentang penghargaan personal yang jelas mengharu biru, tapi tak berbau publisitas. Ini soal ungkapan kebahagiaan yang baru bisa dirangkai dalam hitungan puluhan tahun kemudian.
Tapi tampaknya, kekuatan hikmah itu ternyata memang harus berujung pada sebentuk keniscayaan, bernama pemerataan pada khalayak. Atau sebutlah, dakwah. Atau katakanlah, setiap hal baik akan tercium aroma dan nuansa hingga jauh. Sekuat apa pun seseorang untuk tak ingin tampil di depan khalayak atas derby ikhlas-riya, kebaikan akan menyebar cepat dan berbuah keterkenalan. Sesederhana apa pun niatan seseorang untuk berbuat baik, gelombang penghargaan itu akan datang; bukan lantaran keinginan singgah di hati publik, tapi karena kebaikan itu memang selalu akan diakui adanya.
Pun bila semua tak semegah sekarang. Hirata mengaku, ia bukan seorang sastrawan. Sekali lagi, ia hanya ingin memberikan hadiah pada sang guru tercinta. Segurat dengan bicara Natsir, “Bila pun Masyumi tak ada, saya akan tetap berjuang di jalur Islam.” Artinya, novel itu tetap akan ia persembahkan pada Bu Mus, andai tanpa semua popularitas ini.
Semua tampak semakin meriah ketika analisis yang dikemukakan adalah strukturalis. Denias merilis pentingnya pendidikan, tapi tetap berkolaborasi pada modal raksasa. Faktanya, Denias asli ternyata tengah disekolahkan PT. Freeport. John de Rantau, sang sutradara, mengaku banyak kisah klise di sana; agar film tampak menarik. Gie justru melahirkan dikotomi serius, siapa yang benar-benar berjuang dan siapa yang memanfaatkan perjuangan untuk kepentingan pribadi. Film ini mereputasikan kelompok non-gerakan politik sebagai pahlawan yang sebenarnya. Terlalu tendensius. Semestinya diakui saja bahwa semua kelompok yang ada kala itu turut berkontribusi pada perubahan yang lebih baik. Juga film-film idealis garapan Garin Nugroho yang justru tak bisa dirasakan sebagai karya menjejak di dalam negeri. Ia lebih memilih untuk menjualnya ke luar negeri.
Laskar Pelangi berkisah tentang keresahan luar biasa Hirata atas kondisi republik yang sama sekali tak punya keberpihakan pendidikan kepada rakyat miskin. Tapi ia tak terlalu menyalahkan lingkungan, termasuk negara. Keringatlah kata kuncinya. Ketekunanlah sandi saktinya. Keberanianlah slogan sucinya. Pesan pentingnya, ketergantungan adalah kecualian. Untuk berbuat baik, setiap yang dipunya dapat diberdayakan. Bukan sekolah yang berdinding megah tujuannya. Bukan anak didik yang bermobil. Bukan guru-guru keluaran kampus asing. Bukan fasilitas sekolah yang sangat digital. Ya, ada yang lebih penting. Mental untuk sadar bahwa setiap orang dapat berbuat lebih baik adalah aset yang tak terkira.
Dedikasi tentu berhulu pada rasa kepemilikan yang sangat. Tak ada yang lebih membahagiakan selain merawat semua hal yang dimiliki. Tak ada yang lebih menggairahkan selain mempertahankan kepemilikan itu dengan berbuat yang terbaik. Tak ada yang lebih menyenangkan selain untuk mengabdi pada rasa memiliki, karena sebanding dengan kebaikan.
Hirata punya rasa memiliki itu. Ia tak peduli dengan semua kengerian hidup karena ia telah merasa memiliki sesuatu yang menurutnya, sangat berarti. Ia kesulitan untuk larut dalam kegerahan pemuja kosmopolitan, lantaran rasa kepemilikan yang membuatnya kuat bertahan. Ia bisa jadi ngeri dengan tawaran hidup yang gemerlap, karena bayangan idealnya tentang kesederhanaan yang terwujud atas penghormatan kemanusiaan. Ya, semua itu mencukupi kadar kemanusiaannya.
Dedikasi mensyaratkan kepercayaan diri yang telah dimiliki. Telah dimiliki itu tertaut jiwanya. Akan sakit bila yang satu disakiti. Akan senang bila yang satu berbahagia. Akan kehilangan bila yang satu tak ada. Mereka jelas saling merindukan.