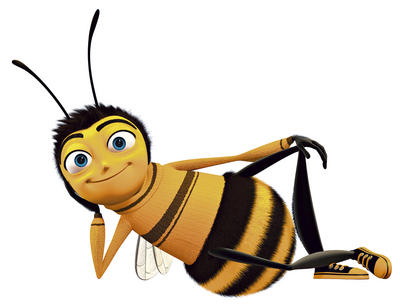Mereka terperangkap dari jerat situasi
Kreasi Bapakku yang trauma revolusi
Mereka jadi korban keadaan frustrasi
Kecewa marah-marah, mendobrak tembok tradisi ....
Tiada hari tanpa pemberitaan terorisme. Suatu ketika, tampak di layar kaca aksi-aksi penggerebekan Densus 88, yang mirip film-film action produksi Hollywood. Pada saat yang lain, disajikan pengawalan pesakitan tersangka teror yang kepalanya telah tertutup rapat, berikut baju khusus yang menandakan bahwa ia memang penjahat paling diburu. Tak kalah atraktif, para polisi yang mengawalnya juga tampak stylist, berkacamata hitam, kostum modis, plus senjata lengkap berstandar internasional.
Publik Indonesia mengharu biru. Rekaman bom bunuh diri di Hotel Ritz Carlton dan JW Marriot berulang kali ditayangkan. Beriring trauma berkepanjangan para korban, juga citra buruk anggota keluarga para tersangka teror, kelompok-kelompok yang merasa tahu pun berspekulasi atas situasi. Terkadang, bendera organ dan teriakan juga dikumandangkan menyusul dukungan atau penolakan aksi pengeboman yang katanya, atas nama Tuhan itu.
Semua terjadi begitu cepat dengan kompleksitas data yang semakin meluber, melibatkan banyak pihak. Semakin data baru ditemukan dan dikonfrontasikan kebenarannya, semakin meninggi pula kekhawatiran publik tentang Indonesia yang ternyata dikecamuki teror terencana, tapi laten.
‘Calon Pengantin’ dari Generasi Muda
Belakangan, respons media mulai melibatkan praduga tentang rawannya kalangan muda akan rekrutmen jaringan pelaku teror. Banyak disebutkan bahwa ‘Calon Pengantin’, istilah untuk calon pelaku bom bunuh diri, didominasi oleh generasi muda. Mereka dahulu adalah anak-anak manis yang taat beribadah, pandai bergaul, dan berprestasi dalam sekolah. Kabarnya, semangat mereka yang tinggi untuk beraktualisasi, berhasil dibelokkan menjadi ‘aksi perlawanan’ berbuah surga.
Modus ini kemudian dilengkapi dengan beberapa data di luar negeri seputar rekrutmen anak-anak muda di berbagai negara oleh jaringan teror internasional, yang konon sukses, karena motif belitan kemiskinan. Terorisme kemudian menemukan arus besarnya, saat didukung oleh anak-anak muda yang berani mati, untuk tujuan keabadian, seperti yang diujarkan pendahulu-pendahulu mereka.
Betapa lantas publik menjadi semakin tahu. Bahwa ternyata, banyak keluarga bermasalah di negeri ini. Faktanya, anggota keluarga tidak tahu-menahu seputar aktivitas ‘para pengantin’. Betapa banyak anak-anak pintar yang seperti tak menemui miliunya. Beberapa dari mereka digiring pada janji-janji keabadian, mengalahkan keharmonisan keluarganya selama ini. Betapa kepedulian sesama masyarakat telah banyak menurun. Siapa sangka, tetangga yang tampak baik itu ternyata adalah perencana atau peracik bom kelas wahid.
Hal ini tentu saja sangat mengkhawatirkan. Generasi muda berkualitas yang berempati tinggi kepada sesamanya sangat menentukan kedamaian republik di masa depan. Bila pendampingan generasi penerus tidak diprioritaskan, bahkan telah rusak perisai norma-norma keluarganya, entah apa yang lantas akan terjadi. Sungguh sulit dan menyisakan sesal yang amat.
Bukan Modus Baru
Bila dirunut agak jauh, modus melibatkan anak-anak muda yang bersemangat tapi labil memang sering terjadi. Sejak dulu, kalangan muda sangat reaktif pada kondisi, dengan penjelasan yang terkadang, agitatif dan provokatif. Kesan heroik menggejala kuat, pertanda energi mereka yang dapat didesain meledak-ledak.
Sedikit data ditulis Tim Weiner, reporter The New York Times, pemenang Pulitzer, dalam buku international best seller-nya berjudul ‘Membongkar Kegagalan CIA: Spionase Amatiran Sebuah Negara Adidaya’. Setidaknya, untuk ukuran dunia, badan intelijen kebanggaan Amerika Serikat itu dapat dijadikan referensi seputar praktik-praktik penguasaan negara lain, berbasis informasi dari agen-agen yang mereka rekrut dan latih.
Dalam buku yang dicetak tahun 2008 itu, Weiner mengemukakan banyak dokumentasi yang ia susun dari 50.000 arsip CIA, hasil wawancara ratusan agen CIA, dan pengakuan sepuluh direkturnya. Sebagian meragukan kelengkapan data Weiner, dengan alasan hanya menyentuh permukaan. Sebagian yang lain merasa perlu untuk tetap mempelajarinya sebagai rujukan.
Weiner menulis rekam jejak Frank Wisner, Kepala Operasi Rahasia CIA, tahun 1952. Ketika itu, ia merencanakan sebuah serangan rahasia besar terhadap Uni Soviet yang ditujukan pada jantung sistem kontrol komunis. Marshall Plan (Program Pemulihan Eropa) pun diubah menjadi pakta-pakta yang menyediakan senjata bagi sekutu Amerika.
CIA mempersenjatai pasukan-pasukan cadangan rahasia untuk memerangi tentara Soviet di seluruh Eropa. Anak buahnya menjatuhkan emas batangan ke beberapa danau, juga mengubur berpeti-peti senjata di pegunungan dan hutan Skandinavia, Prancis, Jerman, Italia, dan Yunani.
Khusus Jerman, CIA berhasil menggalang dukungan dari Young Germans, kelompok muda radikal yang didominasi anggota Hitler Youth. Daftar keanggotaannya bahkan membengkak hingga lebih dari 20.000. Mereka menggunakan senjata-senjata CIA, radio, kamera, dan uang. Parahnya, mereka juga membuat daftar panjang politikus demokratik arus utama Jerman Barat yang akan menjadi sasaran pembunuhan ketika saatnya tiba.
Keluarga Harmonis dan Religius
Kenyataan tentang terekrutnya generasi muda dalam jaringan teror semestinya menjadi kritik telak bagi semua keluarga di Indonesia. Apalagi sebenarnya, lantaran pengaruh pemberitaan teror yang bertubi-tubi, tanpa kepastian kapan semua itu berakhir, dapat membuat kalangan muda pesimis akan masa depan negeri ini, yang berarti juga masa depan mereka. Repotnya, mereka kemudian dibesarkan dalam suasana mencekam, akibat teror yang laten.
Bait lirik lagu di awal tulisan karya Slank, sebuah band kenamaan Indonesia yang memiliki sense of crisis tinggi, dapat membuat siapa pun berpikir tentang pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan religius. Pesan yang ingin disampaikan Slank bermuara pada keseriusan para orang tua untuk mengasihi anak-anaknya pada kadar semestinya. Sebab, tanpa itu, anak akan besar menjadi sosok liar, yang sulit ditengarai maksud dan aktivitas hariannya.
Sementara itu, religiusitas adalah bekal inti. Dengan ilmu agama yang cukup, perintah Tuhan agar manusia menebar rahmat ke seluruh alam, akan mendarah daging dalam hari-hari sang anak. Sebaliknya, bila para orang tua tak lagi memedulikan pendidikan agama anak-anaknya, tragedi demi tragedi akan terus terjadi, hanya lantaran tafsir Kitab Suci yang seringnya, masih sepotong-sepotong. Semoga negeri ini segera entas dari nuansa teror yang jelas sangat tidak diridhai-Nya. Wallahu a’lam bi shawab.