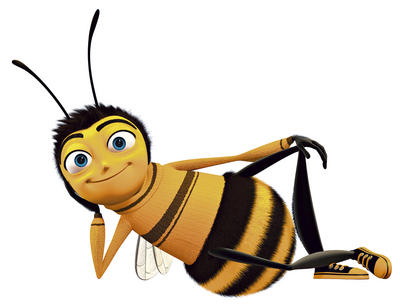“Kalo cowo pinter ketemu cewe pinter, jadinya romantika. Kalo cowo pinter ketemu cewe bodo, yang ada si cewe hamil. Kalo cowo bodo ketemu cewe pinter, terjadilah perselingkuhan. Nah, kalo cowo bodo ketemu cewe bodo, mereka pasti menikah.”
Aku tersenyum. Bukan hanya karena kalimat anekdot pernikahan yang struktur kalimatnya ingin sebanding dengan klasifikasi manusianya Al-Ghazali itu. Aku tersenyum, juga lantaran ketakutan baruku pada perilakuku yang sepertinya tak lagi aku minati kebenarannya.
Belakangan, aku seperti kelu berurusan dengan kriteria norma yang semakin terasa rigid. Aku mendadak tidak ramah pada nilai-nilai yang selama ini aku pegang teguhi itu. Kini, aku berusaha keras menegoisasinya. Aku ingin agak lumer dan menganggap semua nilai itu bisa saja ditafsir ulang; semacam pembenaran ekstra atas keraguanku.
Aku tak tahu, gelagat apa lagi yang tengah berusaha keras merasukiku. Mengapa aku mulai melirik kesimpulan bahwa menikah adalah tindakan bodoh? Meski tentu tidak lantas mengamininya, tapi aku butuh runutan berpikir itu, yang agaknya, terasa kontekstual. Ya, aku tak lagi dapat menemukan keberbanding-lurusan antara kebenaran nilai pernikahan dengan kenyataan tentang pernikahan. Aku mulai merasa, ada cara lain untuk memaknai hubungan spesial yang kata orang, sangat menghabiskan semua hal itu.
Dulu, aku bisa tersungging sinis kalau ada yang menawariku produk KFC, Pizza Hut, atau sejenisnya. Jelas aku punya serentet alasan ideologis hingga teknis. Saking keras kepalanya, bahkan ibuku sempat memberiku saran ketat, “Jadi orang jangan terlalu fanatik.” Miris juga kalau kemudian, selasar doktrin tentang kemandirian bangsa ternyata seperti tak berbanding lurus dengan ridha orang tua seputar kefanatikan. Meski aku juga tak sempat menghubungkan ini dengan perlawanan Nabi Nuh as. pada orang tuanya, pembuat berhala. Ya, aku tetap menganggap, bertradisi makanan transnasional itu tidak keluar dari iman dan Islam. Artinya, aku hanya keberatan atasnya.
Dulu, aku punya cara berbeda menerjemahkan hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan. Atau sebutlah itu, pacaran dan sejenisnya. Pertama, semua ketertarikan seriusku pada perempuan selalu beriring misi sosial. Aku berkesimpulan, akan bisa berbuat banyak pada sesama bila bersama sang cewe. Agak berbangga, agenda-agenda berkunjung ke panti asuhan atau berpikir kemanusiaan sering mewarnai hari-hariku. Senang rasanya menemani seorang cantik yang sangat dicintai orang-orang kurang.
Kedua, hubungan yang terjalin tak pernah menampak formal. Mirip logika Lyotard di film Matrix. Antara ada dan tiada, kata Utopia. Sesekali aku muncul di kediaman, dengan sajian senyum dan servis yang menurutku, paling baik. Pada kali yang lain, aku tak pernah menyapa mereka, karena bermacam alasan sok moralis, seputar agenda-agenda perubahan sosial. Aku sering merasa tak cukup waktu membahagiakan mereka. Tapi terkadang, aku merayah payah, pertanda sebenarnya aku tak pernah mau ditinggalkan. Aku tahu, itu egoisme yang sangat, bernama ‘mau enaknya sendiri’.
Ketiga, selalu ada cara indah untuk mempertahankan kebersamaan. Aku pernah diundang makan bersama, hanya karena ada acara, pamer sayur asem. Beberapa orang tahu, aku begitu menikmati sayur-sayur bernuansa bening. Walau acara makannya bareng-bareng, aku merasa tersanjung. Ada lagi, seorang dari mereka berbangga lantaran berani naik kereta Pramex sendirian, hanya karena ia ingin dianggap dewasa. Ada juga yang mengirimiku buku harian, karena ia tak ingin aku menulis di sembarang tempat. Sekali lagi, seperti ada mahkota Hayam Wuruk di kepalaku.
Keempat, saling kagum menjadi pengikat. Setiap kali bersama mereka, reputasiku naik tak tanggung-tanggung. Setidaknya, aku akan dianggap sebagai seorang waras yang mengerti banyak hal dan banyak orang. Sejauh yang aku tahu, mereka selalu mengabarkan kekaguman mereka atasku pada siapa pun, meski aku juga tahu, mereka terlalu berhati-hati. Artinya, cerita baik itu bukan karena aku benar-benar baik, tapi lantaran mereka tak ingin menyakitiku. Jelas aku juga bertingkah serupa, sekuatku. Aku mengagumi mereka, sebanding dengan semua pembenaranku atas perilaku mereka. Termasuk saat semuanya memilih untuk meninggalkanku. Klasik!!
Dulu, aku selalu menomorduakan gaya hidup. Dedikasilah yang pertama. Aku tak akan rela keluar banyak uang untuk prestise, hingga orang-orang mengira bahwa aku punya kualifikasi ekstra di atas mereka. Termasuk bahwa aku tak ingin dianggap berbeda, bila kemudian membelanjakan banyak uangku untuk membeli buku. Aku juga tak melegal-gampangkan nonton film di bioskop, hanya karena menurutku, tak baik mengamini kecenderungan hedon. Bukan berarti aku tak suka menonton film. Aku ingin memaksa diriku untuk tak segampang itu mengikuti insting keinginanku. Yang parah, hingga kini, aku tak pernah punya selera khusus atas pakaian, baju, atau cara menikmati hidup.
Dulu dan sekarang. Mengapa aku menjadi sangat antusias untuk membenturkan hari-hariku yang telah lewat, dengan hari-hariku kini? Seorang kawan yang pernah menemani hari-hari sulitku sering menjejalkan kekhawatiran menukik, bahwa semestinya aku tak membanding-bandingkan zaman, hanya karena hari ini terasa lebih sulit. Tentu tak baik, begitu katanya.
Benar, aku tidak sedang membanding-bandingkan masa lalu dan kini hanya untuk memilih siapa pemenangnya. Aku hanya ingin kritis pada diriku sendiri, dan berharap tidak tengah bersemangat mendudukkan cara pandangku dengan ukuran baru yang cenderung permisif. Sebab, itu oportunis. Tujuan menghalalkan cara, kata Macchiavelli. Ahistoris karena ingin mengulang zaman yang telah lewat di zaman ini. Karen Armstrong bilang, itu penyebab fundamentalisme.
Makna semua ini juga bukan tuntutan. Karena setahuku, hubungan yang baik adalah hubungan yang berprinsip, memberikan semua hal terbaik; bukan malah sebaliknya. Bila aku masih saja menginginkan banyak hal dari siapa pun, berarti aku tidak pernah belajar dari kesalahanku di masa lalu. Ya, aku belum siap berhubungan.
Bila pun pada kenyataannya aku sangat merindukan semua perbandingan itu untuk melengkapi jiwaku pada hari ini, artinya kadar kemanusiaanku masih ingin dimaklumi. Perilaku bermanusia berkategori ‘meratap’. Betapa aku masih sangat mencintai dunia. Bahwa aku tak ingin dikalahkan. Bahwa aku takut mati, sekaligus takut hidup. Sebab, hingga kini, aku masih saja ingin dimiliki… seutuhnya.
Aku tersenyum. Bukan hanya karena kalimat anekdot pernikahan yang struktur kalimatnya ingin sebanding dengan klasifikasi manusianya Al-Ghazali itu. Aku tersenyum, juga lantaran ketakutan baruku pada perilakuku yang sepertinya tak lagi aku minati kebenarannya.
Belakangan, aku seperti kelu berurusan dengan kriteria norma yang semakin terasa rigid. Aku mendadak tidak ramah pada nilai-nilai yang selama ini aku pegang teguhi itu. Kini, aku berusaha keras menegoisasinya. Aku ingin agak lumer dan menganggap semua nilai itu bisa saja ditafsir ulang; semacam pembenaran ekstra atas keraguanku.
Aku tak tahu, gelagat apa lagi yang tengah berusaha keras merasukiku. Mengapa aku mulai melirik kesimpulan bahwa menikah adalah tindakan bodoh? Meski tentu tidak lantas mengamininya, tapi aku butuh runutan berpikir itu, yang agaknya, terasa kontekstual. Ya, aku tak lagi dapat menemukan keberbanding-lurusan antara kebenaran nilai pernikahan dengan kenyataan tentang pernikahan. Aku mulai merasa, ada cara lain untuk memaknai hubungan spesial yang kata orang, sangat menghabiskan semua hal itu.
Dulu, aku bisa tersungging sinis kalau ada yang menawariku produk KFC, Pizza Hut, atau sejenisnya. Jelas aku punya serentet alasan ideologis hingga teknis. Saking keras kepalanya, bahkan ibuku sempat memberiku saran ketat, “Jadi orang jangan terlalu fanatik.” Miris juga kalau kemudian, selasar doktrin tentang kemandirian bangsa ternyata seperti tak berbanding lurus dengan ridha orang tua seputar kefanatikan. Meski aku juga tak sempat menghubungkan ini dengan perlawanan Nabi Nuh as. pada orang tuanya, pembuat berhala. Ya, aku tetap menganggap, bertradisi makanan transnasional itu tidak keluar dari iman dan Islam. Artinya, aku hanya keberatan atasnya.
Dulu, aku punya cara berbeda menerjemahkan hubungan khusus antara laki-laki dan perempuan. Atau sebutlah itu, pacaran dan sejenisnya. Pertama, semua ketertarikan seriusku pada perempuan selalu beriring misi sosial. Aku berkesimpulan, akan bisa berbuat banyak pada sesama bila bersama sang cewe. Agak berbangga, agenda-agenda berkunjung ke panti asuhan atau berpikir kemanusiaan sering mewarnai hari-hariku. Senang rasanya menemani seorang cantik yang sangat dicintai orang-orang kurang.
Kedua, hubungan yang terjalin tak pernah menampak formal. Mirip logika Lyotard di film Matrix. Antara ada dan tiada, kata Utopia. Sesekali aku muncul di kediaman, dengan sajian senyum dan servis yang menurutku, paling baik. Pada kali yang lain, aku tak pernah menyapa mereka, karena bermacam alasan sok moralis, seputar agenda-agenda perubahan sosial. Aku sering merasa tak cukup waktu membahagiakan mereka. Tapi terkadang, aku merayah payah, pertanda sebenarnya aku tak pernah mau ditinggalkan. Aku tahu, itu egoisme yang sangat, bernama ‘mau enaknya sendiri’.
Ketiga, selalu ada cara indah untuk mempertahankan kebersamaan. Aku pernah diundang makan bersama, hanya karena ada acara, pamer sayur asem. Beberapa orang tahu, aku begitu menikmati sayur-sayur bernuansa bening. Walau acara makannya bareng-bareng, aku merasa tersanjung. Ada lagi, seorang dari mereka berbangga lantaran berani naik kereta Pramex sendirian, hanya karena ia ingin dianggap dewasa. Ada juga yang mengirimiku buku harian, karena ia tak ingin aku menulis di sembarang tempat. Sekali lagi, seperti ada mahkota Hayam Wuruk di kepalaku.
Keempat, saling kagum menjadi pengikat. Setiap kali bersama mereka, reputasiku naik tak tanggung-tanggung. Setidaknya, aku akan dianggap sebagai seorang waras yang mengerti banyak hal dan banyak orang. Sejauh yang aku tahu, mereka selalu mengabarkan kekaguman mereka atasku pada siapa pun, meski aku juga tahu, mereka terlalu berhati-hati. Artinya, cerita baik itu bukan karena aku benar-benar baik, tapi lantaran mereka tak ingin menyakitiku. Jelas aku juga bertingkah serupa, sekuatku. Aku mengagumi mereka, sebanding dengan semua pembenaranku atas perilaku mereka. Termasuk saat semuanya memilih untuk meninggalkanku. Klasik!!
Dulu, aku selalu menomorduakan gaya hidup. Dedikasilah yang pertama. Aku tak akan rela keluar banyak uang untuk prestise, hingga orang-orang mengira bahwa aku punya kualifikasi ekstra di atas mereka. Termasuk bahwa aku tak ingin dianggap berbeda, bila kemudian membelanjakan banyak uangku untuk membeli buku. Aku juga tak melegal-gampangkan nonton film di bioskop, hanya karena menurutku, tak baik mengamini kecenderungan hedon. Bukan berarti aku tak suka menonton film. Aku ingin memaksa diriku untuk tak segampang itu mengikuti insting keinginanku. Yang parah, hingga kini, aku tak pernah punya selera khusus atas pakaian, baju, atau cara menikmati hidup.
Dulu dan sekarang. Mengapa aku menjadi sangat antusias untuk membenturkan hari-hariku yang telah lewat, dengan hari-hariku kini? Seorang kawan yang pernah menemani hari-hari sulitku sering menjejalkan kekhawatiran menukik, bahwa semestinya aku tak membanding-bandingkan zaman, hanya karena hari ini terasa lebih sulit. Tentu tak baik, begitu katanya.
Benar, aku tidak sedang membanding-bandingkan masa lalu dan kini hanya untuk memilih siapa pemenangnya. Aku hanya ingin kritis pada diriku sendiri, dan berharap tidak tengah bersemangat mendudukkan cara pandangku dengan ukuran baru yang cenderung permisif. Sebab, itu oportunis. Tujuan menghalalkan cara, kata Macchiavelli. Ahistoris karena ingin mengulang zaman yang telah lewat di zaman ini. Karen Armstrong bilang, itu penyebab fundamentalisme.
Makna semua ini juga bukan tuntutan. Karena setahuku, hubungan yang baik adalah hubungan yang berprinsip, memberikan semua hal terbaik; bukan malah sebaliknya. Bila aku masih saja menginginkan banyak hal dari siapa pun, berarti aku tidak pernah belajar dari kesalahanku di masa lalu. Ya, aku belum siap berhubungan.
Bila pun pada kenyataannya aku sangat merindukan semua perbandingan itu untuk melengkapi jiwaku pada hari ini, artinya kadar kemanusiaanku masih ingin dimaklumi. Perilaku bermanusia berkategori ‘meratap’. Betapa aku masih sangat mencintai dunia. Bahwa aku tak ingin dikalahkan. Bahwa aku takut mati, sekaligus takut hidup. Sebab, hingga kini, aku masih saja ingin dimiliki… seutuhnya.