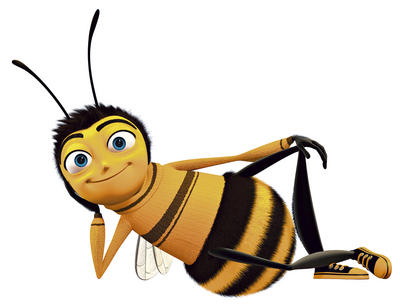“Mak, ini Jakarta, ya?” tanya bocah laki-laki itu pada ibunya. Ia tampak terus melekatkan pandangannya ke langit kelam Jakarta yang dipenuhi suasana aneh, dan sepertinya belum pernah ia temui. Dengan mimik penuh apresiasi, perempuan berusia lebih dari setengah baya itu pun mengiyakan pertanyaan buah hatinya.
“Di sini banyak orang kaya ya, Mak?” tanya si anak untuk kedua kalinya. “Iya....” Kali ini, mereka berhenti di depan sebuah toko yang berareal teras cukup luas. Tentu saja toko itu telah tutup, lantaran hari sudah beranjak tengah malam. Setelah sedikit berbenah, dengan menggelar selembar kain untuk tidur, mereka pun berbaring di depan toko itu.
“Orang kaya pasti makannya enak-anak ya, Mak?” tanya sang anak sambil menatap ibunya. “Ya dong. Udah, cepat tidur! Jangan sampai kita bangun lebih siang dari pemilik toko. Biar kita tidak diusir lagi,” jelas sang ibu singkat. Mereka kemudian terlelap bersama balutan malam Jakarta yang belakangan dipenuhi resesi ekonomi dan sangat potensial melahirkan chaos.
***
Cuplikan kisah tersebut dapat dijumpai pada film klasik Indonesia garapan Arifin C. Noor tentang G 30 S/PKI. Di zaman Orde Baru, film kolosal ini menjadi tontonan wajib, setiap kali memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Karena di zaman Orba stasiun TV swasta belum sebanyak sekarang maka praktis hampir semua mata di negeri ini pun melayangkan pandangannya pada scene-scene dramatis penculikan jenderal-jenderal TNI AD dan penumpasan G 30 S itu. Walau beberapa kalangan meragukan validitas film yang dikemas semi dokumenter tersebut, tetap saja tak mampu menghapus kenangan menyakitkan tragedi kemanusiaan seputar kudeta berdarah dan akhirnya konflik bersenjata antaranak bangsa tersebut. Sejarah kelam yang semoga tidak terulang kembali di masa datang.
Yang menarik, dengan bahasa yang sangat sederhana, Arifin seperti ingin menyampaikan pesan penting pada pemirsa tentang hubungan erat antara perasaan tertindas kaum papa dengan revolusi. Kesenjangan ekonomi pada waktu itu menjadi alasan kuat bertumbuhkembangnya ketidakpuasan, juga gejolak sosial. Jadi sebenarnya, bahkan tanpa doktrin marxis yang rigid pun, perseteruan antara si kaya dan si miskin tampak seperti keniscayaan bila kesenjangan itu dibangun atas ketidakadilan.
Arifin tentu saja melihat semua peristiwa mengerikan itu dari dekat. Ia dapat mendemonstrasikan semua ketakutan yang terjadi ketika itu dalam gambar, suara, dan skenario yang mengagumkan tentu karena ia sangat mengerti situasi yang berkembang, dan apa yang menyebabkannya. Ia mampu membingkai harapan banyak pihak tentang bangsa yang satu, tanpa ada lagi celah sikap—sedikit pun—untuk saling menyakiti, lantaran potongan-potongan kisah tentang kekejaman manusia yang haus kekuasaan itu benar-benar menghantuinya. Ia berpesan dalam gambar bahwa kalau tak hati-hati, korban akan berjatuhan seiring dengan kerakusan dan keserakahan anak bangsa yang satu atas anak bangsa yang lain.
Menyejarahkan Kemiskinan
Sepanjang waktu, mencatat kemiskinan memang pekerjaan sulit. Bagaimana tidak sulit? Siapa sih yang mau dianggap miskin? Siapa sih yang mau diperdebatkan penderitaan hidupnya lantaran kurang makan? Siapa sih yang bangga dengan predikat keluarga tidak mampu?
Deretan angka-angka pun berusaha menjelaskan kondisi riil yang ada seputar kemiskinan. Tapi, apa kata dunia? Banyak yang bilang, angka bisa saja dimanipulasi untuk mendongkrak popularitas. Ada yang yakin, kalau data-data kuantitatif itu hanya akal-akalan beberapa orang yang tidak menginginkan kemiskinan sebagai borok prestasinya. Bahkan ada yang ragu bahwa kemiskinan sering dijadikan komoditas untuk meraih simpati publik. Semacam pemahaman umum tentang ‘data yang diragukan’ bila telah berkutat di wilayah kemiskinan. Sekali lagi, ada tendensi prestisius seputar baik-buruk menyuguhkan kemiskinan di mata publik.
Tapi sudahlah. Bagaimana dengan kemiskinan yang memang benar-benar ada? Bagaimana dengan berita tentang korban frustrasi karena dibekap kemiskinan? Apalagi, bukan karena mereka yang tak bekerja keras. Apalagi, bukan karena mereka yang hanya bisa meminta-minta. Apalagi, bukan pula karena keserakahan mereka menjadi miskin. Apalagi, semua ini karena ketegaan sesama manusia yang memiliki perilaku takut miskin, berlebihan.
Lihatlah, dari tahun 1867 sampai 1878, Hindia telah menyumbang f187 juta bagi kas kerajaan Belanda. Sebuah angka fantastis bila dibandingkan dengan kesejahteraan rakyat Hindia yang masih sangat rendah. Ketika itu, rakyat Hindia hidup jauh di bawah garis kemiskinan. Hindia bahkan dapat menghidupi rakyat Belanda, walau mungkin, masyarakat negeri kincir angin itu tidak bekerja sama sekali.
Lihatlah, Orde Lama dianggap tak mampu menyejahterakan rakyat Indonesia dalam dua dekade setelah kemerdekaan. Orla dinilai sangat retoris, dan tak memedulikan penderitaan rakyat miskin. Inflasi yang mencapai lebih dari 600 persen di akhir pemerintahan Orla bahkan dapat dijadikan tumpuan untuk menganalisis keberhasilan orde ini mengurusi rakyat miskin.
Lihatlah, Orde Baru dianggap membangun infrastruktur ekonomi semu. Walau swasembada beras tercipta, harga-harga rendah, dan inflasi kecil, rakyat miskin tetap saja tak dapat dientaskan. Berpuluh tahun kaum miskin bahkan dianggap merepotkan pemerintahan kota besar. Gedung-gedung pencakar langit memenuhi sudut-sudut perkotaan, tapi nasib petani tidak jelas juntrungannya. Mereka bisa memproduksi beras dalam skala besar, tapi tak dapat memiliki komoditas lain, lantaran harga beras tidak sepadan dengan biaya sekolah, teknologi, transportasi, juga komunikasi.
Lihatlah, Orde Reformasi pun masih mandul membangun kerangka ekonomi yang stabil. Selain kedekatan mereka dengan modal asing, pembelaan mereka pada masyarakat miskin terjejali dengan dominasi agenda politik yang bertajuk demokratisasi tak terarah. Isu-isu tentang kemiskinan seperti hilang di tengah ingar-bingar manuver politik para pejabat dan wakil-wakil rakyat di parlemen.
Bila demikian halnya, Knut Hamsund, seorang novelis Norwegia awal abad ke-20, tiba-tiba menjadi sosok yang penting. Pada 1890, salah satu novelnya berjudul Sult (lapar), mampu membuat publik Norwegia terkesima. Novel ini bercerita tentang seorang penulis miskin yang sangat kesusahan makan. Setiap hari dia menggelandang di jalanan kota Christiania karena tak mampu membayar sewa kamar dan membeli makanan. Tapi, ia tetap menulis.
Kabarnya, Hamsund menulis novel ini dalam keadaan benar-benar lapar. Dan ia berhasil menceritakan kepapaannya itu dalam kadar optimistis yang sangat tentang hari yang lebih baik. Mentalitas tentang penyampaian isu kemiskinan kepada publik, tapi dengan keinginan kuat untuk berubah. Bukan malahan mengelak dari semua sejarah tentang kemiskinan.
“Kalau saja aku punya sesuatu untuk dimakan, sedikit saja, pada hari secerah ini!” tulis Hamsund.