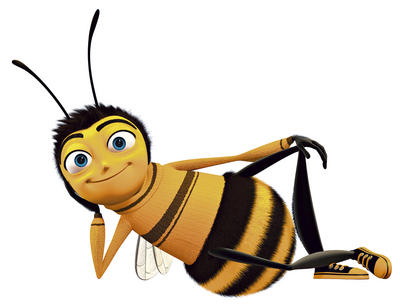A blinding flash of white light
Lit up the sky over Gaza tonight
People running for cover
Not knowing whether they're dead or alive
Malam Minggu ini aku beruntung. Entah selip hikmah apa yang membuatku membetik ingin, mendengarkan lagu Michael Heart, We Will Not Go Down (Song for Gaza). Kemarin-kemarin aku hampir malas membicarakan Palestina, lantaran tak ada lagi yang bisa benar-benar kuperbuat untuk menganulir misil-misil F-16 Israel. Obama mania seperti tak peduli, bahkan merayakan selebrasi pelantikan Presiden AS dengan gegap gempita. Itu kan terhubung erat. Ridwan Saidi bilang, Barack Obama satu marga dengan Ehud Barak. Aduh, diagnosis sama-sama Yahudi ini makin bikin kepalaku belingsatan.
Seorang kawan meneleponku, khusus bicarakan konflik ini. Aku masih bisa bicarakan banyak hal, lantaran bicara dengan kawan dekat; suasana batinku pun terdukung. Tapi kalau terus-terusan membicarakannya, bisa-bisa aku tak tidur tiga hari. Kepala sesak, banyak alternatif langkah yang bisa diusulkan, tapi kelu karena semua hal itu tak ada gunanya. Setidaknya, mendingan sewaktu di komisariat dulu, yang masih bisa teriak-teriak di jalan, kalau AS-Israel gila-gilaan. Aku bahkan bertekad tak menyentuh produk-produk bisnis mereka.
Yang paling parah, aku semakin sadar, bahwa semua kekuatan aku punya—bahkan kadang aku membanggakannya—benar-benar tak bisa berbuat banyak. Semua terjadi begitu saja. Aku sangat tahu, banyak mayat mati sia-sia di negeriku sendiri. Westerling bahkan menggasak sekitar 40 ribu nyawa. Jutaan orang mati pada Revolusi Kemerdekaan juga Tragedi 1965. Setiap hari ada saja yang mati karena kurang makan, aborsi, praktik kriminal, ketidakadilan orang kaya atau negara, kecelakaan, trafficking, dan deretan kasus lagi yang tak terbaca. Aku lebih tahu kalau kemiskinan dan kesewenang-wenangan terjadi di depan hidungku.
Tapi seharusnya tak harus memisah-misahkannya. Aku marah pada agresi Israel dan aku juga marah pada orang kaya yang tak mau peduli pada kere-kere di sekitarnya. Tak perlu menganggap di antaranya lebih penting. Toh seringnya, tak ada yang benar-benar bisa aku perbuat untuk semua itu.
They came with their tanks and their planes
With ravaging fiery flames
And nothing remains
Just a voice rising up in the smoky haze
Aku bilang ke kawanku, “Di dalam Al-Quran, hanya disebutkan kata Yahudi sekali saja. Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk.” Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (Al-Baqarah: 120)
Aku jelaskan, Yahudi itu kepercayaan. Ada Yahudi, ada bani Israil. Yahudi itu kepercayaan yang didakwahkan kepada bani Israil oleh Musa as. Bani Israil itu bangsa. Nah, belakangan, banyak salah tafsir yang memang dimobilisasi oleh manusia-manusia yang mengaku Yahudi, salah satunya. Menggelindinglah citra bahwa Yahudi sama dengan bani Israil atau Israel itu. Orang Israel merasa bahwa Yahudi adalah bangsa pilihan Tuhan, dengan ‘Tanah yang Dijanjikan’. Sementara, orang-orang yang membenci Israel menganggap, semua Yahudi sama dengan Israel. Padahal, ada Yahudi yang tak setuju zionisme. Banyak juga bukan Israel, yang perilakunya seperti Israel.
We will not go down
In the night, without a fight
You can burn up our mosques and our homes and our schools
But our spirit will never die
We will not go down
In Gaza tonight
Bagiku, agresi Israel memetakan—istilah Hegel—keharusan sejarah. Ada pendakuan dan pengakuan, tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang tak bisa berbuat apa-apa. Kalau dulu, hubungan intim Israel-AS tampak samar-samar, kini dunia tahu, keduanya bermasalah. Dulu, Timur Tengah tampak sangat suci, sekarang mungkin, Kakbah menyesal diturunkan di sana. Dulu, Indonesia yang lemah di dunia internasional masih bisa dipelintir-pelintir; saat ini semua tahu, diplomasi menjadi bagian yang mubazir. Apa gunanya kecewa dan mengutuk Israel, kalo veto masih di AS? Buat apa berusaha mengakomodasi kemarahan rakyat dengan kaum Muslimin terbesar ini, tapi tak punya F-16 lebih dari 15 unit?
Dan… semua orang kota terus-terusan melahap produksi dagang pro-Israel: Coca-Cola, Huggies, River Island, McDonalds, Clinique, Disney, Donna Karan, Starbucks, GAP, Garnier, Perrier, Kotex, Sanex, JO Malone, Lancome, Libbys, Tchibo, Loreal, Marks & Spencer, Kleenex, Maybelline, Nestle, Vittel, Revlon, wonderbra.
Women and children alike
Murdered and massacred night after night
While the so-called leaders of countries afar
Debated on who's wrong or right
But their powerless words were in vain
Bahwa tak boleh ada yang bertekuk lutut pada keadaan seperti apa pun. Bahkan dengan korban nyawa lebih dari 3000 orang. Bahwa tak pantas menyerah pada kesulitan semisal apa pun. Bahwa pantang meringis untuk sesuatu yang jelas tak layak dihormati; apalagi menyembahnya.
And the bombs fell down like acid rain
But through the tears and the blood and the pain
You can still hear that voice through the smoky haze